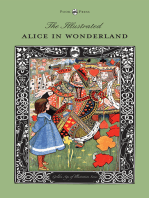Professional Documents
Culture Documents
Pengertian Fatwa
Uploaded by
Dani LiverpudlianOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Pengertian Fatwa
Uploaded by
Dani LiverpudlianCopyright:
Available Formats
Pengertian Fatwa Secara bahasa fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum.
MenurutEnsiklopedi Islam, fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Disebutkan dalam Ensiklopedi Islam bahwa si peminta fatwa baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal itu, disebabkan fatwa seorang mufti atau ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa biasanya cenderung dinamis, karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif. Tindakan memberi fatwa disebut futya atau ifta, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut mustafti. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya. Futya pada dasarnya adalah profesi independen, namun dibanyak negara Muslim menjadi terkait dengan otoritas kenegaraan dalam berbagai cara. Dalam sejarah Islam, dari abad pertama hingga ketujuh Hijriyah, negaralah yang mengangkat ulama bermutu sebagai mufti. Namun, pada masa-masa selanjutnya, pos-pos resmi futya diciptakan, sehingga mufti menjadi jabatan kenegaraan yang hierarkis, namun tetap dalam fungsi keagamaan. Untuk dapat melaksanakan profesi futya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, beragama Islam. Kedua, memiliki integritas pribadi ('adil), ketiga ahli ijtihad (mujtahid) atau memiliki sesanggupan untuk memecahkan masalah melalui penalaran pribadi. Berbeda dengan seorang hakim, seorang mufti bisa saja wanita, orang buta, atau orang bisu, kecuali untuk jabatan kenegaraan. Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid. Pada mulanya praktik fatwa yang diberikan secara lepas dan belum ada upaya untuk membukukan isi fatwa ulama-ulama tersebut. Fatwa pertama kali dikumpulkan dan sebuh kitab pada abad ke-12 M. Mazhab Hanafi memiliki sejumlah kitab fatwa sepertiaz-Zakhirat al-Burhaniyah, kumpulan fatwa Burhanuddin bin Maza (wafat 570 H/1174). Inilah kitab kumpulan fatwa pertama. Mazhab Maliki memiliki kitab kumpulan fatwa bertajuk al-Mi'yar alMagrib yang berisi fatwa-fatwa al-Wasyarisi (wafat 914 H/1508 M). Mazhab Hanbali juga memiliki sejumlah kitab fatwa, yang paling terkenal adalah Majmu al-Fatawa. Di Indonesia juga ada sejumlah buku kumpulan fatwa, seperti Tanya Jawab Agama dan Kata Berjawab yang diterbitkan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, selain itu ada juga Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,
serta Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama. Kedudukan Fatwa Karena fatwa merupakan penjelasan hukum syara atas persoalan tertentu yang tidak semua orang dapat memahaminya, maka kedudukan fatwa menjadi sangat penting (selama masyarakat belum memiliki kemampuan untuk berijtihad). Berikut pendapat para ulama mengenai pentingnya fatwa: Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan berijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan terhenti[Mafaahim al-Islaamiyyah, juz 1, hal. 240]. Kedudukan fatwa dalam Islam sangatlah penting dan tidak bisa dengan mudah diabaikan, apalagi digugurkan. Karena sangat pentingnya dengan keberadaan fatwa dalam Islam, sampai-sampai beberapa ulama berpendapat diharamkan tinggal di sebuah tempat yang tidak terdapat seorang mufti yang bisa dijadikan tempat bertanya tentang persoalan agama (Lihat Kitab Al Bahr Ar Raiq 6/260, Al Furu 4/119, Al Majmu 1/47, Kasyaf Al Qana 4/177). Maka dari itu, wajib bagi penguasa untuk memperhatikan sarana-sarana penting guna mempersiapkan para mufti dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, sekaligus melarang bagi mereka yang tidak mempunyai keahlian dalam berfatwa. (Lihat Al Majmu 1/ 69, Ilam Al Muwaqqiin 4/214, Al Faqih wa Al Mutafaqqih 2/55, Al Ahkam Al Sulthoniyah, 55). Imam Al Qarafi sendiri menyatakan bahwa mufti dihadapan Allah ibarat kedudukan eoarang penerjemah di hadapan hakim, yang menerjemahkan keputusan hukum, tanpa mengurangi dan menambahnya, sedangkan qadhi adalah aparat untuk melaksanakan putusan itu (Lihat, Kitab Ihkam fi Tamyizi Al Fatawa min Al Ahkam, 30). Kaitan Fatwa dan Ijtihad Meskipun fatwa dan hasil ijtihad keduanya sama sama terkait dengan hokum syara, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan tersebut antara lain terlihat dari sisi definisi. Jika fatwa hanya sebatas penjelasan hokum syara, maka ijtihad adalah proses menggali hokum syara dari dalil-dalil yang bersifat dzanniy dengan mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan, hingga dirinya tidak mungkin lagi melakukan usaha lebih dari itu. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaitan antara hasil ijtihad dan fatwa adalah: Seorang mujtahid berijtihad untuk menggali hukum syara atas sesuatu yang tidak secara jelas disebutkan status hukumnya dari Al Quran maupun As Sunnah, kemudian jika masyarakat luas belum dapat memahami hasil ijtihad itu secara sempurna, maka seorang mufti berkewajiban memberikan fatwa untuk menjelaskan perkara tersebut. Karena kedudukannya yang berbeda, maka syarat untuk berijtihad dan berfatwa pun berbeda. Seseorang layak melakukan ijtihad jika: Pertama, memahami dalil-dalil samiyyah yang digunakan untuk membangun kaedah-kaedah hukum. Yang dimaksud dengan dalil samiyyah adalah al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Seorang mujtahid harus memahami alQuran, Sunnah, dan Ijma, klasifikasi dan kedudukannya. Ia juga harus memiliki
kemampuan untuk memahami, menimbang, mengkompromikan, serta mentarjih dalil-dalil tersebut jika terjadi pertentangan. Kemampuan untuk memahami dalildalil samiyyah dan menimbang dalil-dalil tersebut merupakan syarat pokok bagi seorang mujtahid.[5] Kedua, memahami arah penunjukkan dari suatu lafadz (makna yang ditunjukkan lafadz) yang sejalan dengan lisannya orang Arab dan para ahli balaghah. Syarat kedua ini mengharuskan seseorang yang hendak berijtihad memiliki kemampuan dalam memahami seluk beluk bahasa Arab, atau kemampuan untuk memahami arah makna yang ditunjukkan oleh suatu lafadz. Oleh karena itu, seorang mujtahid atau mufti harus memiliki kemampuan bahasa yang mencakup kemampuan untuk memahami makna suatu lafadz, makna balaghahnya, dalalahnya, serta pertentangan makna yang dikandung suatu lafadz serta mana makna yang lebih kuat setelah dikomparasikan dengan riwayat tsiqqah dan perkataan ahli bahasa. Seorang mujtahid tidak cukup hanya mengerti dan menghafal arti sebuah kata berdasarkan pedoman kamus. Akan tetapi, ia harus memahami semua hal yang berkaitan dengan kata tersebut dari sisi kebahasaan. Sedangkan menurut Imam Syaukaniyyang disebutkan dalam Kitab Fath al-Qadiirseorang mufti haruslah orang yang shaleh, dan selalu menyelaraskan dengan pendapat-pendapat yang terpilih, dan tidak boleh mengamalkan fatwa dari mufti-mufti fasiq yang tidak boleh mengeluarkan fatwa. Sebab, fatwa termasuk urusan agama, sedangkan pendapat orang fasiq dalam urusan agama tidak boleh diterima (ghairu al-maqbuul). Ketentuan ini didasarkan pada kenyataan bahwa, pengkhianatan orang fasiq terhadap agama telah tampak dengan jelas. Sesungguhnya, inayah Allah swt dalam persoalan-persoalan syariat hanya akan tercapai dengan mentaati Allah swt, dan berpegang teguh kepada tali ketakwaan. Telah disebutkan di dalam al-Quran al-Kariim, Wattaquu al-Allah wa yuallimukum al-Allah[Bertaqwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian.[TQS Al-Baqarah (2): 282] [Durrur al-Hukkaam fi Syarh Majallat al-Ahkaam, juz 13, hal. 162]. Metode Penetapan Fatwa Karena fatwa merupakan penjelasan hukum syara, maka fatwa tidak dapat ditetapkan secara sembarangan. Penetapan fatwa harus didasarkan pada prinsip-prinsip ijtihad, yakni fahm al-nash (memahami nash) dan fahm alwaaqi al-haaditsah (memahami realitas yang terjadi). Fahmu al-nash adalah upaya memahami dalil-dalil syariat hingga diketahui dilalah alhukm(penunjukkan hukum) yang terkandung di dalam dalil tersebut. Sedangkan fahmu al-waaqi al-haaditsah adalah upaya mengkaji dan meneliti realitas yang hendak dihukumi agar substansi persoalannya bisa diketahui, serta hukum syariat yang paling sesuai dengan realitas tersebut. Penetapan atau penolakan terhadap fatwa tidak boleh dilakukan berdasarakan asas manfaat atau nafsu seperti dalam kasus fatwa MUI terkait golput dan keharaman rokok. Fatwa Pada Masa Rasulullah SAW Pada masa hidupnya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak ada kesulitan. Semua hukum yang dibutuhkan masyarakat diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung menyampaikannya kepada orang banyak. Misalnya hukum
shalat membayar zakat. Tuhan memerintahkan dengan wahyu perantaraan Malaikat Jibril, langsung kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan beliau sesudah menerima lantas membacakan wahyu itu kepada para sahabat yang hadir ketika itu. Allah berfirman, kata beliau :
Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' Pada ayat ini Allah menyuruh shalat dan mengeluarkankan zakat. Nabi berfatwa, ummat menerima. Kalau dalam perintah itu belum terang maka ummat bertanya kepada Nabi, yakni bagaimana caranya shalat itu, apa rukunnva, apa syaratnya dan pula perintah itu wajibkah atau sekedar anjuran. Begitu juga zakat, apakah macamnya harta yang mesti dizakatkan, kepada siapa harus diberikan, berapa banyaknya harta yang wajib dizakatkan. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kesemuanya itu dan menerangkan dengan sejelas-jelasnya apa maksud Allah dengan wahyu-Nya itu, karena tugas Nabi selain menyampaikan wahyu kepada ummat, juga menjelaskan maksud wahyu itu.
Artinya : "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang di turunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia . Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." (QS Al-Maidah : 67). Dan dalam ayat lain disebutkan:
Inilah maksud firman Allah :
Artinya : Keterangan-keterangan (mu'jizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan". (QS An Nahl : 44). Jadi tugas Rasulullah ialah menyampaikan wahyu dan menjelaskan isi dan maksudnya. Kalau umpamanya ada ummat bertanya kepada Nabi dalam hukum sesuatu yang tidak/belum diturunkan wahyunya, maka Nabi menjawab, boleh jadi dengan menunggu wahyu atau beliau saja menerangkan tanpa wahyu yang dengan perantaraan Malaikat Jibril. Yang wahyu dinamakan al-Quran, dan yang langsung dari Nabi dinamakan hadits-hadits Nabi atau Sunnah Rasul. Yang wahyu pada waktu itu dituliskan, tetapi hadits-hadits tidak boleh dituliskan, karena takut akan campur aduk dengan wahyu. Hadits-hadits semuanya disimpan dalam dada dan dihafal di luar kepala oleh para sahabat Nabi yang mendengarnya. Contohnya:
1. Sekumpulan orang bertanya kepada Nabi tentang hukum bersetubuh dengan isteri ketika mereka membawa bulan (haidh), maka Nabi menjawab dengan wahyu Ilahi, begini:
Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." . (QS AI Baqarah :222). Kemudian ayat ini menimbulkan soal lagi karena dalam ayat tersebut disebutkan : 'Janganlah kamu mendekati mereka". Apakah benar-benar tidak boleh mendekati mereka? Hat ini diterangkan Nabi pula dengan ucapan beliau, begini:
Artinya : "Buatlah apa saja kecuali bersetubuh". (Riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim juz Xll hal. 211). Pertanyaan yang pertama dijawab dengan wahyu dan yang kedua dijawab dengan hadits. 1. Sekumpulan orang bertanya kepada Nabi tentang hukum meminum minuman keras dan berjudi. Demikian pula mereka bertanya tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Nabi menjawab dengan wahyu Ilahi, begini
Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir". (QS Al Baqarah : 219). 2. Seorang bertanya kepada Nabi tentang air laut, apakah boleh dipakai buat berwudhu' atau tidak. Beliau menjawab pertanyaan itu dengan tidak menunggu wahyu, sebagai tersebut dalam kitab hadits, begini:
, ,
Artinya : "Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang lakiIaki bertanya kepada Rasulullah tentang air laut, maka Nabi menjawab : "Air laut itu membersihkan (boleh dipakai untuk berwudhu'). Ikannya yang mati pun boleh dimakan" . (Hadits Tirmidzi - SahihTirmidzi juz I halaman 88). Demikianlah bahwa hukum-hukum pada masa Nabi tidaklah mendapatkan kesulitan karena apa saja boleh ditanyakan kepada beliau. Fatwa Pada Masa Sahabat
Sepeninggalnya Rasulullah SAW, nabi telah mewariskan dua sumber hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan dalam pemecahan segala permasalahan yang ada, yaitu al Quran dan Sunnah nabi. Kehidupan bermasyarakat yang semakin dinamis, memingkinkan timbulnya permasalahanpermasalahan baru yang harus dipecahkan, untuk itu para ulama baik dikalangan sahabat dan tokoh Islam lainnya, berkeawjiban menegakkan hukum tasri pada zamannya masing-masing. Kewajiban tersebut, sebagaimana AW. Khalaf simpulkan berupa; penjelasan kepada umat Islam tentang persoalanpersoalan yang membutuhkan penjelasan dan interpretasi dari teks-teks al Quran dan as Sunnah. Kemudian, menyebarluaskan dikalangan umat Islam tentang hal-hal yang mereka hafal dari ayat-ayat al Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Lalu, memfatwakan kepada masyarakat tentang peristiwa-peristiwa hukum dan urusan peradilan yang belum terdapat ketetapan hukumnya (Abdul Wahab Khalaf. 5, 2002). Adapun sumber dan metode penetapan hukum pada masa sahabat dapat disarikan dari al Quran, hadits Rasulullah SAW, dan Ijtihad Sahabat. Sedangkan dalam pandangan Khudari Bik, sumber pengambilan hukum pada masa sahabat dapt di ambil dari; al Quran sebagai landasan utama, kemudian as Sunnah, Qiyas atau Rayu (pendapat), lalu Ijma yang bersandar pada al Quran, sunnah dan qiyas (Khudari Bik. 259). Alur pemecahan masalahnya adalah ketika terjadi suatu permasalahan baru atau persengketaan, maka para sahabat dan ahli fatwa mencari ketetapan hukumnya melalui al Quran, apabila mereka menemukan pemecahannya dalam al Quran, maka mereka menerapkan hukum tersebut.Jika ternyata tidak ditemukan keterangan dalam al Quran, maka para ulama membangun fatwa yang bersandar pada as Sunnah. Jika memang tidak didapati keterangan yang spesifik tentang permasalahan yang muncul, maka para ulama melakukan ijtihad untuk menyelesaikannya,baik dengan ijtihad ataupun qiyas dengan pertimbangan utuk kemaslahatan umat manusia. Argumentasi kenapa setiap permasalah harus di ambil pemecahannya dalam al Quran dan hadits nabi, itu berdasar pada keterangan dalam QS.An Nisa, 59. Sementara dasar argumentasi yang mengharuskan ijtihad sahabat merupakan bagian dari hukum Islam adalah bersandar pada apa yang pernah terjadi ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabal menjadi Qadhi di negeri Yaman (lihat AW. Khalaf.49, 2002). Sementara karakteristik tasyri pada zaman sahabat yang bisa dilihat adalah, fiqih pada zaman ini sejalan dan serasi dengan segala permasalahan yang muncul kala itu. Tidak terbatas pada apa yang pernah terjadi pada masa Rasul. Sementara yang memegang kendali fatwa dan qadha dalam berbagai permasalahan penting adalah para khalifah. Pada zaman ini, al Quran telah di bukukan dan mushaf telah disentralisasikan, sehingga kaum Muslim dapat terhindar dari pertikaian tentang sumber utama bagi masyarakat Islam yang sebelumnya mereka terpecah kepada beberapa kelompok.Kemudian sunnah pada zaman ini, masih terjaga kemurniannya, tidak terkontaminasi dengan kebohongan dan penyimpangan
karena zaman yang begitu dekat dengan Rasulullah dan para penukilnya adalah para sahabat Rasul. Selain itu pada zaman ini, muncul satu sumber baru bagi perundangundangan silam yaitu Ijma dan itu sering terjadi karena memang sudah dilakukan dan semua asbabnya memadai. Kemudian para sahabat tidak mewariskan fiqih yang tertulis, namun mereka hanya mewariskan fatwa dan hokum yang tersimpan dalam dada para sahabat dan disampaikan dengan cara penghikayatan (Rasyad Hasan Khalil. 75, 2009). Pada awal kekhalifahan sahabat Abu Bakar as Shidiq, ia memgang kekuasaan tasyri mengenai problem yang belum ada ketetapan hukumnya menurut nash dalam suatu lembaga tasyri yang dibentuk dan di hadiri oleh para sahabat. Abu Bakar dikenal sebagai orang yang jujur dan disegani, ia merupakan salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, karena kedeketannya dengan Rasul itulah, ia mempunyai pengertian yang dalam tentang jiwa keislaman di banding dengan sahabat yang lain. Di ceritakan dalam riwayat yang dikemukan al Baghawi dalam kitabnya Masahih as-Sunnah, ia menuturkan Abu Bakar, kalau dihadapkan suatu kasus perselisihan kepadanya, maka beliau mencari ketetapan hukumnya dalam al Quran. Kalau beliau mendapat ketetapan hukumnya dalam al Quran, maka beliau memutuskan perkara meraka dengan ketetapan menurut al Quran. Jika tidak ditemukan dalam al Quran beliau menetapkan ketetapan hukumnya menurut ketetapan Rasulullah SAW dalam sunnah, kemudian jika mendapat kesulitan beliau berkonsultasi dengan sesame sahabat, kemudian berkata telah dihadapkan kepadaku suatu permasalahan, apakah di antara kalian ada yang mengetahui bahwa nabi telah menetapkan hukumnya perihal masalah seperti ini?.Adakalanya sekelompok sahabat berkumpul dan menyebutkan bahwa nabi SAW pernah menetapkan hukumnya. Kemudian Abu Bakar berkata: segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara kita orang yang menghafal sunnah nabi kita. Selanjutnya pada masa khalifah sahabat Umar bin Khatab, beliau juga banyak melahirkan keputusan atau ketetapan-ketetapan hukum mengenai permasalahan yang muncul pada zamannya. Pemerinyahan Umar bin Khattab berlangsung selama sepuluh tahun (634-644 M). Umar merupakan sahabat yang mempunyai karakter pemberani dan tegas dalam menentukan persoalan. Beberapa keputusan dan ketetapan hukum yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab di antaranya mengenai talak tiga yang di ucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika, di anggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk sebagai suami istri, kecuali salah satu pihak (istri), kawin terlebih dahulu dengan orang lain. Garis hukum ini ditentukan oleh Umar berdasarkan kepentingan para wanita karena di zamannya banyak pria yang dengan mudajh menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada istrinya untuk dapat dicerai dan kawin dengan yang lainnya. Hal ini pada zaman sahabat Abu Bakar sebagai khalifah di anggap sebagai talak satu.Umar menetapkan garis hukum demikian, untuk mendidik suami supaya tidak menyalahgunakan wewenang yang berada dalam tangannya.
Dalam masalah zakat, al Quran menegaskan bahwa golongan yang berhak menerima zakat salah satunya adalah para muallaf (orang yang baru masuk Islam).Maka pada masa Umar, para muallaf tidak lagi di beri zakat, dengan alasan pemberian zakat pada muallaf diberikan karena mereka memerlukan perhatian dan bantuan dari ummat Islam yang kuat dalam memeluk Islam. Umar bin khattab menganggap bahwa pada zamannya, Islam telah kuat kedudukannya dalam msyarakat, dan para muallaf pada zamannya telah cukup kuat untuk mempertahankan keimanannya. Dalam hal hukum potong tangan yang dijelaskan al Quran surah al Maidah. 38, bagi orang yang mencuri di ancam hukuman potongan tangan. Pada masa Umar, teerjadi kelaparan dalam masyarakat semenanjung Arabia, maka dalam keadaan masyarakat yan ditimpa kelaparan tersebut, ancaman terhadap pencuri yan disebutkan dalam al Quran tidak diberlakukan pada zaman kepemimpinan khalifah Umar. Berdasarkan pertimbangan keadaan (darurat) dan kemaslahatan masyarakat. Kemudian dalam al Quran surah al Maidah.5,terdapat ketentuan yang membolehkan pria Muslim menikahi wanita ahli kitab (wanita Yahudi dan Nasrani).Akan tetapi khalifah Umar melarang perkawinan yang demikian, untuk melindungi wanita Muslim dan keamanan rahasia Negara (Mohammad Daud Ali. 175, 2009). Selanjutnya masuk ke dalam masa ke khalifahan Utsman bin Affan yang berlangsung dari tahun 644-656 M, produk hukum yang dibangunnya dapat juga dilihat dari jasa-jasa besarnya yang paling penting yaitu tindakannya telah membuat al Quran standar (kodifikasi al Quran). Standarisasi al Quran dilakukannya karena pada masa pemerintahannya, wilayah Islam telah sangat luas dan di diami oleh berbagai suku dengan bahasa dan dialek yang berbeda. Karena itu, dikalangan pemeluk agama Islam, terjadi perbedaan ungkapan dan ucapan tentang ayat-ayat al Quran yang disebarkan melalui hafalan. Perbedaan cara mengungkapkan itu, menimbulkan perbedaan arti, saat berita ini sampai kepada Usman, ia lalu membentuk penitia yang di ketuai Zaid bin Tsabit untuk menyalin al Quran yang telah dihimpun pada masa khalifah Abu Bakar yang disimpan oleh Hafsah (janda nabi Muhammad SAW).Panitia tersebut bekerja secara disiplin, menyalurkan naskan al Quran ke dalam Mushaf untuk dijadikan standar dalam penulisan dan bacaan al Quran di wilayah kekuasan Islam pada waktu itu. Pada zaman ke khalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib (656-662 M), Ali tidak banyak mengambangkan hukum Islam, dikarenakan Negara tidak stabil. Di sana timbul bibit-bibit perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam yang bermuara pada perang saudara yang kemudian menimbulkan kelompokkelompok. Di antaranya dua kelompok besar yakni, kelompok Ahlussunah Wal Jamaah dan Syiah.
You might also like
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19653)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5783)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2475)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionFrom EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (12941)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19993)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionFrom EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2391)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (2552)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6503)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)From EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (7769)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationFrom EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationRating: 4 out of 5 stars4/5 (2385)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (3265)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksFrom EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksRating: 4 out of 5 stars4/5 (7086)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersFrom EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersRating: 4 out of 5 stars4/5 (2306)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleFrom EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HoleRating: 4 out of 5 stars4/5 (4609)
- Don Quixote: [Complete & Illustrated]From EverandDon Quixote: [Complete & Illustrated]Rating: 4 out of 5 stars4/5 (3845)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)From EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (4345)



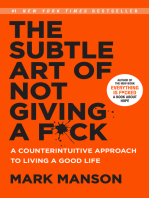











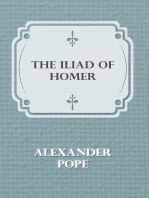







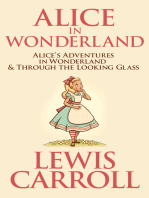

![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)