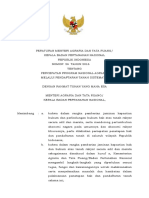Professional Documents
Culture Documents
Polisi Dalam
Uploaded by
Fadli Riski MOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Polisi Dalam
Uploaded by
Fadli Riski MCopyright:
Available Formats
POLISI DALAM PEMILU
(Dimuat di Majalah Kompolnas, edisi Juli 2013) Judul tulisan ini sebenarnya ingin memberi pemaknaan yang jamak mengenai posisi kepolisian di dalam tahun politik, yaitu periode menjelang, saat, dan pasca pemilihan umum hingga terbentuknya kekuasaan legislatif baru atau terpilihnya presiden baru. Berbagai artikel telah menjelaskan kompleksitas relasi antara pemilu dengan fungsi kepolisian. Tidak hanya dipandang sebagai kekuatan yang difungsikan untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, namun lebih dari itu, kepolisian dapat menjadi subjek yang masuk dalam pusaran agenda politik itu sendiri. Satu tahun ke depan Indonesia akan disibukkan dengan agenda politik besar pemilihan umum. Bahkan sebelum itupun, hampir setiap tahun dilakukan pemilihan kepala daerah/gubernur yang juga menyerap energi publik, tidak terkecuali kepolisian. Dalam setiap pemilihan tersebut, tuntutan terhadap maksimalisasi kinerja kepolisian meningkat. Terutama di dalam menjaga keamanan masyarakat dari ekskalasi tensi politik elit yang sering menjalar ke akar rumput. Sangat jamak, bahkan seakan telah menjadi tradisi politik lokal, dalam setiap proses pemilihan kepala daerah selalu diwarnai oleh letupan-letupan kecil maupun besar yang mengiringi persaingan elit dalam perebutan kekuasaan. Bahkan tidak jarang pula berujung pada munculnya korban materi maupun jiwa. Pengendalian situasi ini tentu tidak hanya menjadi beban kepolisian, karena pada dasarnya adab dalam politik hakikinya adalah damai dan sepenuhnya merupakan pilihan-pilihan yang beretika dari elit dan massa. Menggunakan pemikiran Jurgen Habermas, politik seharusnya persaingan sehat pada ranah publik, dengan kebebasan berekspresi, namun beretika, tidak memaksakan kehendak, terlebih kekerasan. Kesadaran elit dan massa karenanya merupakan kunci demokrasi yang sehat, selain ditunjang pula oleh aturan main atau administrasi yang jelas dan adil. Kepolisian karenanya adalah agen yang berada di luar arena, yang murni bertindak dalam pengamanan, mengawal mekanisme administratif pemilihan itu sendiri. Namun, kenyataan politik di Indonesia belum sepenuhnya memperlihatkan kedewasaan berdemokrasi. Hal yang membuat kepolisian tidak hanya disibukkan dengan pengerahan kekuatan untuk pengendalian massa atau mendeteksi potensi gangguan keamanan. Namun juga berpotensi diseret dalam pusaran politik itu sendiri. Walker dan Waterman (2008) menjelaskan, situasi politik, khususnya pemilihan umum, dapat mempengaruhi sikap publik terhadap polisi, sekaligus mempengaruhi perilaku polisi itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan di Costa Rica, Mexico, dan Amerika Serikat, diketahui bahwa pemolisian dapat menjadi agenda politik (dipolitisasi) karena persoalan penegakan hukum masuk dalam kampanye partai. Pada titik inilah muncul tuntutan terhadap netralitas dan profesionalitas kepolisian di dalam proses politik pemilihan umum. Walker dan Waterman juga memberikan analisasi bahwa, perkembangan demokrasi di sebuah negara turut pula mempengaruhi performa kepolisian, yang kemudian dapat berimplikasi terhadap sikap kepolisian itu sendiri dalam politik. Performa kepolisian di sebuah negara demokrasi baru sering merupakan cerminan dari belum terkonsolidasinya manajemen negara secara keseluruhan.
Belum berjalan maksimalnya prinsip-prinsip demokrasi dan kepemerintahan yang baik dalam sebuah negara sangat rentang membawa institusi kepolisian yang seharusnya imparsial masuk ke dalam arus politik dan berpihak. Situasi yang seharusnya tidak boleh terjadi untuk menciptakan masyarakat yang aman dan terlindunginya kepentingan banyak pihak. Keberpihakan institusi negara seperti kepolisian tentu akan menjauhkan realita dari mimpi demokrasi. Analisa Walker dan Waterman ini memberi ruang analisa yang lebih luas dari sekedar bagaimana polisi berperan dalam pengamanan pemilihan umum. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, diskusi tentang polisi dan pemilu memiliki makna yang jamak. Meskipun bila direduksi mengerucut pada dua isu besar, yaitu profesionalitas dan netralitas. Profesionalitas tentunya terkait dengan fungsi pemolisian di dalam pemilu, sedangkan netralitas terkait dengan jarak politik lembaga kepolisian dengan aktor-aktor politik yang bertarung di dalam pemilihan umum, termasuk jarak kepolisian itu sendiri dengan proses politik. Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil jelas merupakan indikator negara demokratis yang dewasa. Oleh karenanya, untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan menindak pelanggaran yang berunsur pidana sesuai undang-undang. Di negara-negara demokratis maju sekalipun, pemilihan umum bukanlah proses yang dapat bebas 100% dari permasalahan, penyimpangan, hingga yang memiliki unsur pidana. Penelitian Topo Santoso, et.al (2006) mencatat sejumlah tindak pidana yang terjadi dalam pemilihan umum tahun 2004, di antaranya adalah; dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, pemalsuan ijazah calon, penghinaan terhadap calon lain, politik uang, penghasutan dan adu domba, penyalahgunaan kartu pemilih, hingga mengubah hasil rekapitulasi hasil suara. Dalam analisanya, pelanggaran-pelanggaran seperti ini masih terjadi pada tahun 2009 dan juga berpotensi terjadi pada tahun 2014. Dalam pengalaman pemilihan kepala daerah yang hampir setiap tahun dilakukan di Indonesia, jenis pelanggaran tersebut kerap terjadi dan menjadi faktor yang dapat meningkatkan ekskalasi konflik antar elit yang menjalar ke massa. Pengalaman pemilihan umum di Indonesia sejak 1999 termasuk pemilihan-pemilihan kepala daerah cukup memberi preseden yang seakan menjalar dari satu waktu dan tempat ke waktu dan tempat yang lain. Di sini, peran kepolisian menjadi sangat penting dan sentral. Administrasi dan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak akan dapat bekerja maksimal tanpa peran kepolisian dalam mencegah dan melakukan penindakan terhadap tindak pidana pemilu. Nota Kesepahaman antara POLRI dengan KPU untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu pada Jaruani 2013 lalu adalah bukti pentingnya kerjasama tersebut. KPU dan POLRI menyadari bahwa setiap tahanan pemilu selalu memiliki potensi gangguan keamanan. Profesionalitas kepolisian, melalui peran bimbingan masyarakat dan intelijen, diperlukan untuk menyusun langkah antisipasi dan deteksi dini. Namun demikian, profesionalitas pada dasarnya memerlukan netralitas. Walker dan Waterman telah memberikan analisa bagaimana rentannya institusi kepolisian dalam momen pemilihan umum untuk masuk ke dalam pusaran arus politik itu sendiri. Sebagai institusi penegak hukum, profesionalitas kepolisian diperlukan untuk menjamin pemilu yang bebas, jujur, adil. Selain memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan penindakan, kemampuan personil
kepolisian dalam deteksi dini dan penyadaran masyarakat agar konformis terhadap hukum merupakan modal yang menentukan kesuksesan pesta demokrasi untuk menghasilkan legislator dan pemimpin baru. Namun, profesionalitas tidak akan kontributif bila tidak disertai dengan netralitas. Netralitas dalam hal ini dimaknai sebagai jarak yang tegas dari kepolisian dengan aktor-aktor yang bertarung dalam pemilu dan tentunya jarak dengan proses politik itu sendiri. Netralitas ini ditandai dengan tidak bertindak diskriminatif dan menjalankan tugas dengan proporsional. Seperti meneruskan pemeriksaan dugaan-dugaan pelanggaran yang telah diidentifikasi sebelumnya oleh bawaslu. Pada hari ulang tahun POLRI ke-67, 1 Juli 2013 lalu, presiden menekankan kembali agar POLRI menjunjung tinggi kode etik dalam tugas serta memberikan pelayanan publik yang lebih responsif dan profesional. Instruksi ini tentu bukan tanpa alasan mengingat masih banyaknya kasus pelanggaran etika anggota kepolisian yang kasat mata bagi publik. Hal yang tentu dikhawatirkan dapat mempengaruhi profesionalitas dan netralitas kepolisian di dalam momen besar pemilihan umum. Dalam kerangka berfikir Evans, et.al (1992), profesionalisme dan netralitas kepolisian ini dapat ditandai dengan sikap yang responsif, tidak pasif. Tidak hanya dalam penindakan yang tidak membedakan kasus per kasus atau kelompok per kelompok, namun juga dalam langkah antisipasi terhadap potensi-potensi gangguan keamanan. Bila menggunakan kerangka berfikir Evans, et.al ini, dapat dimaknai bahwa sikap responsif kepolisian dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi bimbingan dan penyuluhan yang memberi ruang interaksi lebih luas bagi kepolisian untuk tidak hanya menghimbau namun mendialogkan sejumlah persoalan yang nantinya dapat diantisipasi secara bersama dengan masyarakat. Seperti mengajak elit untuk dapat lebih arif dalam berkompetisi sehingga tidak justru menjadi pemicu bentrok yang tidak perlu di tingkat akar rumput, sebagaimana jamak diperlihatkan oleh pemilihan kepada daerah di Indonesia setiap tahunnya. Peran partai politik dan elit sangat krusial dalam tradisi politik patron-klien di Indonesia, sehingga responsifitas kepolisian dapat dimulai jauh sebelum momen pemilihan tersebut berlangsung dengan mengajak elit untuk berkompetisi dengan beretika. Rentang waktu hingga pertengahan 2014 nanti merupakan waktu yang sangat krusial bagi kepolisian untuk mulai menyusun atau merevisi langkah-langkah strategis untuk mengamankan tahun politik ini. Selain meningkatkan kembali profesionalitas, kepolisian perlu menjalankan strategi-strategi yang tidak hanya bersifat umum dan normatif, namun juga mengoptimalkan peran-peran handal anggota pada tingkat lokal. Walker dan Waterman turut merumuskan pemahaman bahwa kepolisian pada dasarnya institusi yang lokal, non partisan yang hanya melaksanakan fungsi melayani dan melindungi. Dalam kerangka ini, kepolisian akan menjadi institusi yang lebih responsif dan tidak terbawa oleh arus politik.
You might also like
- Permen Esdm 11 2021 Pelaksanaan Usaha KetenagalistrikanDocument163 pagesPermen Esdm 11 2021 Pelaksanaan Usaha KetenagalistrikanShas4No ratings yet
- Permen Percepatan Prona PDFDocument21 pagesPermen Percepatan Prona PDFAriefيوليانتوNo ratings yet
- Permen Percepatan Prona PDFDocument21 pagesPermen Percepatan Prona PDFAriefيوليانتوNo ratings yet
- P ('t':'3', 'I':'669566548') D '' Var B Location Settimeout (Function ( If (Typeof Window - Iframe 'Undefined') ( B.href B.href ) ), 15000)Document11 pagesP ('t':'3', 'I':'669566548') D '' Var B Location Settimeout (Function ( If (Typeof Window - Iframe 'Undefined') ( B.href B.href ) ), 15000)Fadli Riski MNo ratings yet
- Cara Pasang, Jalankan & Atur FirefoxDocument1 pageCara Pasang, Jalankan & Atur FirefoxFahmi Wahyu TrihasnoNo ratings yet