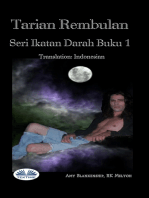Professional Documents
Culture Documents
Aku Dan Kakakku
Uploaded by
tiara_nien0 ratings0% found this document useful (0 votes)
35K views11 pagesThis is actually an entry for some short-story competition a few years ago. I didn't win (actually, I don't know what happened to the competition afterward), and this is also not much of a story, of course. But if you read it, please give some feedback so I can improve my writing quality! ^_^
Original Title
Aku dan Kakakku
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentThis is actually an entry for some short-story competition a few years ago. I didn't win (actually, I don't know what happened to the competition afterward), and this is also not much of a story, of course. But if you read it, please give some feedback so I can improve my writing quality! ^_^
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
35K views11 pagesAku Dan Kakakku
Uploaded by
tiara_nienThis is actually an entry for some short-story competition a few years ago. I didn't win (actually, I don't know what happened to the competition afterward), and this is also not much of a story, of course. But if you read it, please give some feedback so I can improve my writing quality! ^_^
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 11
Kakakku dan Aku
Aku memiliki seorang kakak perempuan.
Orangnya agak aneh, dan sering membuat masalah.
Kisahku dengannya telah dimulai sejak aku lahir hingga sekarang, dan
nampaknya takkan pernah berakhir.
***
Aku berumur tiga tahun, kakakku berumur tujuh tahun.
Saat itu, kelas kakak mengadakan pembacaan karangan murid-muridnya
kepada para orangtua murid, dan dengan mengejutkan, karangan kakakku terpilih
menjadi salah satu karangan terbaik. Ibuku yang bangga membawaku, yang masih
terlalu kecil untuk ditinggal sendiri di rumah, ke sekolah.
Kuketahui bertahun-tahun setelahnya, (saat itu aku masih terlalu kecil untuk
mengerti) tema karangannya adalah ‘Keluarga’. Tapi berbeda dari karangan teman-
temannya yang normal yang menulis tentang ayah atau ibunya, kakakku yang baru
kelas dua SD memilih aku sebagai tema utama. AKU.
Ia memulai pembacaannya, dengan rasa percaya diri yang tinggi dan semangat
yang meledak-ledak, khas dirinya.
“Adikku, karya Adinia Kirara.” , dia berhenti sejenak dan memandang aku dan
ibu. Ibu tersenyum menyemangati. Kakak melanjutkan.
“Aku punya seorang adik laki-laki. Namanya Adiwan Prayogi. Dia berumur
tiga tahun, beda empat tahun denganku. Dia lahir tanggal 25 Maret 1987. Bertepatan
dengan hari ulang tahunku yang keempat. Aku sayaaaaaa...ang sekali pada adikku.
Dia lucu sekali. Pipinya tembem, bulat dan berwarna merah, tiap aku melihat dia, aku
teringat pada roti coklat yang masih panas. (sepertinya pada kalimat ini seluruh orang
tua disitu tertawa). Matanya bulat, bundar seperti kelereng, dan warnanya coklat tua.
Aku teringat pada bola kaca kalau sedang memandang matanya.
“ Meskipun dia sangat lucu, Yogi kadang-kadang nakal. Aku sering kesal
karena dia. Dia pernah mengencingi dadaku ketika aku membuka popoknya. Tapi
kata ayah itu karena anunya selalu berdiri jadi tidak bisa pipis dengan benar. Kata
ayah kalau dia sudah besar anunya akan baik-baik saja dan tidak akan mengencingi
orang lagi.”
Dan semua orangtua di kelas itu, termasuk gurunya, meledak tertawa.
Menertawakan anuku.
Tapi karena kakakku terlalu kecil atau terlalu bodoh, dia tidak menyadari apa
yang ditertawakan orang-orang dan melanjutkan membaca, tetap dengan riang dan
bersemangat.
“Dia juga belum bisa pup dengan benar, jadi dia tidak ke kamar mandi dulu
kalau mau pup. Tapi dia langsung pup di tempat. Waktu ibu terlambat mengganti
popoknya, (kata ibu, mukanya menjadi sangat merah ketika kakak menyebutkan
bagian ini) Yogi mengoles-oles pupnya ke lantai, membuat gambar-gambar lucu.
Lantai rumah jadi kotor dan sampai sekarang masih ada bekasnya, tapi aku bangga
karena adikku bisa menggambar.”
Lagi-lagi semua orangtua di kelas, termasuk guru, meledak tertawa.
Menertawakan pupku.
Masih banyak kelanjutan karangan kakakku, terlalu memalukan jika kuingat
lagi semuanya.
Aku tidak mengerti, tapi ingatan ibu-ibu tampaknya memang sangat kuat.
Beberapa tahun berselang (dan aku akhirnya sudah mencapai usia cukup untuk
berpikir jernih, dan tentunya, merasakan malu), ibu-ibu tetangga yang kadang-kadang
berkunjung ke rumah masih suka tertawa dan menanyai dimana bekas pupku itu.
***
Aku berumur enam tahun, kakakku berumur sepuluh tahun.
Hari ini hari pertamaku masuk sekolah.
Kakakku yang khawatir pada adik kecilnya menggandeng tanganku sepanjang
hari dan terus-terusan bertanya, “Yogi, kamu mau pipis? Atau mau makan sekarang?
Kakak bawa chiki dan permen buat Yogi...”
Sampai akhirnya guru kami berdua datang dan memisahkan genggaman
tangannya padaku.
Kakak terlihat lebih khawatir daripada diriku.
Ketika pulang sekolah, ia menghampiri kelasku dan langsung menggamit
tanganku dan mengajakku pulang. Aku yang masih kecil senang karena punya
seorang kakak yang hebat.
Namun seminggu kemudian, saat teman-teman mulai mengejekku manja, aku
menepis tangannya.
Aku pulang sendiri, dengan membusungkan dada, dengan kebanggaan seorang
anak usia enam tahun yang tidak ingin dikatai manja.
Yang tidak kuketahui adalah kakak terus mengawasiku dari belakang,
memastikan tak ada mobil yang akan menabrakku, tak ada anjing yang akan
menggigitku, dan tak ada anak yang menggangguku.
Aku sempat diganggu sekelompok anak kelas tiga yang kerjanya mengompas
anak-anak yang lebih kecil. Beberapa hari kemudian mereka tidak menunggu di depan
sekolah lagi. Bahkan, mereka menghilang entah kemana.
Aku baru mengetahui alasannya besok. Guru dan beberapa orangtua datang
kerumah kami untuk memarahi kakak. Anak-anak itu ternyata terbaring di rumah
dengan kepala benjol-benjol.
Kakakku hanya tersenyum lebar saat diinterogasi.
***
Aku berumur delapan tahun, kakakku berumur dua belas tahun.
Kakakku baru saja masuk SMP, dan akhirnya setelah sekian tahun lamanya
aku tidak satu sekolah dengannya.
Enam bulan setelahnya, aku yang duduk di kelas 3 SD dan kakak dibagi rapor
pada hari yang sama. Papa menemaniku pergi ke pembagian rapor.
Pak Guru memulai dengan memuji, “Yogi sangat pintar, pak. Semua nilainya
tidak ada yang dibawah sembilan, dan kelakuannya sehari-hari juga baik... Sama
seperti kakaknya dulu...”
Sama seperti kakaknya.
Sama seperti kakaknya, adalah kata-kata yang selalu kuterima tiap aku
menerima nilaiku.
Sepulang sekolah, kami bertemu dengan mama dan kakak yang juga baru
pulang dari SMP.
Kakakku lagi-lagi mendapat nilai sempurna, dan dia juga meraih peringkat
satu, tidak hanya di kelasnya, tapi juga di sekolahnya.
Aku hanya meraih peringkat ketiga di sekolah.
Saat itulah aku tahu, ada yang salah.
***
Aku berumur sepuluh tahun. Kakakku berumur empat belas tahun.
Pada umur ini, aku mengalami cinta monyet pertamaku. Kepada teman
sekelasku, seorang gadis manis berkepang dua yang bernama Nadia. Bahkan namanya
pun manis.
Berdasarkan apa yang kutonton di sinetron-sinetron di TV, cowok-cowok
tokoh utamanya mengutarakan cinta mereka dengan berbagai cara. Setelah mengalami
pergulatan batin yang cukup memusingkan untuk anak berumur sepuluh tahun,
akhirnya kuputuskan untuk menulis surat.
Pada saat itu, bagiku menulis surat buat cewek benar-benar perkara hidup-mati
yang sangat penting. Kucurahkan segenap hati, seluruh tenagaku, untuk merangkai
kata-kata di surat itu. Aku membayangkan, kalau Nadia membaca surat ini dia akan
balas menyukaiku.
Surat itu akhirnya selesai ditulis. Dengan hati-hati kulipat dan kumasukkan
kedalam amplop pink yang kubeli khusus untuk ini. Kemudian kutulis di bagian
depan amplop : Buat Nadia, dari Yogi..
Sempurna.
Sampai aku membuat kesalahan besar.
Meletakkan surat itu begitu saja di atas meja belajarku.
Kakak senang menerobos keluar masuk kamarku seakan itu kamarnya sendiri.
Dan tebak apa yang ditemukannya? Voila. Sepucuk surat cinta.
Kakak Nadia, Nino (sialnya) seumur dengan kakakku, dan mereka berdua
(sialnya), sekelas.
Jadi kakakku yang polos berpikir, ‘Yogi nulis surat buat Nadia! Aku kasihin
ah.’ Dan dia menyampaikannya pada Nadia, tanpa kuketahui, dan tentu saja, dia
menyampaikannya lewat KAKAKNYA.
Keesokan harinya, setelah pada pagi harinya aku datang terlambat ke sekolah
mencari-cari surat tersebut, aku dihadang oleh sekelompok anak SMP telat puber
yang dipimpin oleh tidak lain tidak bukan kakak Nadia. Yang paling parah adalah
ketika aku dipukuli, segerombolan anak berkerumun menonton dan menyoraki, dan
salah satunya Nadia.
Aku pulang dengan memar-memar di wajah, dan ketika dengan tanpa rasa
bersalah kakakku dengan panik bertanya apa yang terjadi, aku menjadi sangat heran.
Kenapa ada saudara laki-laki yang ingin melindungi saudara perempuannya seperti
kakaknya Nadia sementara aku justru ingin melakukan sebaliknya.
***
Aku berumur sebelas tahun, kakakku berumur lima belas tahun.
Kami sedang makan malam, dan ayah bertanya pada kakak yang baru masuk
SMA. “Rara, cita-cita kamu mau jadi apa nanti?”
Kakak menjawab dengan tegas tanpa keraguan sedikitpun, “Rara mau jadi
dokter yah! Rara ingin bisa mengobati banyak orang, terus bisa jagain ayah, ibu dan
Yogi supaya selalu sehat.”
Ketika ayahku terdiam, kakak terlihat agak tidak enak, dan melanjutkan, “Oh,
soal biaya kuliahnya, jangan khawatir yah! Rara bakal nyari beasiswa, jadi ayah
tenang aja!”
Di tengah-tengah keramaian suasana makan malam...
Ayahku yang menjitak kakak dan meneriakkan hal-hal semacam anak bodoh
dan kakakku tidak sepantasnya khawatir soal biaya karena dia, ayahnya akan
mengurus semua itu dan dia tinggal terima beres...
Ibuku yang tertawa dan mengatakan hal-hal semacam ayah tidak perlu
sombong, kalau kakak bisa mendapat beasiswa maka itu akan baik untuk semua…
Kakakku yang nyengir membenarkan kata-kata ibu…
Aku memutuskan satu hal.
Ketika aku dewasa nanti, aku akan berkarir di bidang sosial. Kerja apapun
oke, yang penting jauh dan tidak berkaitan dengan kedokteran.
***
Aku berumur dua belas tahun, kakakku berumur enam belas tahun.
Pada suatu sore, ia muncul di kamarku.
“Apa?”, tanyaku heran.
“Nggak ada apa-apa kok...”, katanya. Dia tampak ragu-ragu melanjutkan
kalimatnya. “Yogi... kamu...”.
“Ya?”
“Golongan darah kamu apa? Pernah diperiksa nggak?”
Aku heran dengan pertanyaan aneh ini, “Emm.. O kalau nggak salah.
Kenapa?”
Aku menangkap adanya perubahan raut wajah kakak, namun dengan cepat ia
memasang kembali raut mukanya yang biasa.
“Oh. Begitu. Terima kasih ya Yogi.”
“Kak. Kenapa?”
Ia menghentikan langkahnya keluar kamarku dan berkata, “Nggak apa-apa.
Ada… yang lagi Rara cari. ”
Kakak berlalu dari kamarku, meninggalkan aku yang bingung.
Dia memang aneh, tapi kali ini anehnya lebih aneh.
***
Aku berumur tiga belas tahun, kakakku berumur tujuh belas tahun.
Tubuhku mulai meninggi pada usia ini, dan sekarang pulalah aku mulai
menginjak masa puber. Dengan segera aku menjadi lebih tinggi dari kakakku, dan
suaraku pun pecah. Di usia ini pula pola pikirku mulai berkembang lebih dewasa,
melebihi anak-anak seumurku, selain hormon mungkin juga karena pengaruh buku-
buku dan koran yang selalu kubaca. Sementara aku bertumbuh semakin maskulin dan
dewasa, ukuran tubuh dan kedewasaan kakak sepertinya tidak beranjak dari dirinya
yang berumur empat belas tahun.
Dia masih suka tertawa lebar dan tidak memakai make-up apapun ke
sekolahnya. Sikapnya pun tidak berubah manja didepan cowok atau merubah gaya
berjalannya yang tomboy. Diantara teman-temannya yang centil dan terlihat dewasa,
kakak seperti tertinggal di masa SMP.
Kadang-kadang, aku mau tidak mau memperhatikan, akhir-akhir ini kakak
terlihat menjadi agak pendiam. Dia juga jarang tertawa lagi. Awalnya kukira ini
adalah hal yang baik, mungkin kakak sudah menjadi lebih dewasa. Tapi kusadari
belakangan, dia bukan menjadi lebih pendiam, melainkan lebih murung.
Suatu saat aku datang ke sekolahnya untuk mengantarkan sesuatu, dan dari
tepi gerbang aku melihatnya duduk sendirian di tepi lapangan. Seorang cewek
menghampirinya, seperti mengatakan sesuatu, kemudian pergi dari hadapan kakak
dan bergabung dengan segerombolan anak lainnya dan tertawa.
Aku tidak mendengar apa yang mereka katakan, tapi aku tahu yang mereka
tertawakan adalah kakakku.
Malam harinya, raut muka kakak terlihat gelap.
Dan ketika kami mencuci piring bersama setelah makan malam, ia bertanya
padaku, “Yogi, Rara kayak anak kecil ya?”. Jawaban yang jujur adalah ya, tapi aku
memutuskan balik bertanya, “Kenapa nanya begitu?”.
Ia terlihat salah tingkah, tapi kemudian berkata pelan, “Soalnya… Rara nggak
seperti teman-teman yang lain,”
Jawaban ini benar-benar tidak kusangka. Selama ini, kakak memang
BERBEDA dari anak-anak yang lain. Kecerdasan otaknya tentu saja, lalu
kepribadiannya yang ceria dan hangat memang agak berbeda dari gadis-gadis lain
yang rata-rata menjaga tawa dan kata-kata (apalagi didepan cowok). Begitu berbeda
hingga kadang-kadang surreal. Ia bisa tertawa lebar dan menyerukan semangat
dengan ceria sampai rasanya ia bukan seorang remaja, tapi masih seorang anak yang
senang-senangnya bermain.
Dan aku menyangka kakak tidak pernah mempedulikan pendapat orang lain.
“Kak… lo sering dikerjain ya di sekolah?”, sahutku tanpa bisa ditahan.
Dia terlihat kaget, namun kemudian bercerita dengan lancar. Rupanya selama
ini kakak selalu diejek teman-temannya karena sikapnya dan pola pikirnya yang
sederhana. Mereka mengatakan dia aneh, dan lama kelamaan dari ejekan verbal
berkembang menjadi tindakan.
“Terus, mereka bilang apa lagi?”, tanyaku, tanpa sadar tinjuku makin
mengepal seiring ceritanya.
“Sudahlah, nggak apa-apa kok Yogi. Kamu juga nganggap Rara aneh, kan?”
Aku terperangah tak percaya, “Kakak nyamain gue dengan mereka?”
Mata kakak membesar menatapku, “Eh, bukan begitu, tapi, Rara kira…
gimana yah, Yogi gak suka sama Rara? Kalau Rara lihat, Yogi kesal terus kalau
didekat Rara...”
Giliranku yang tergagap menjawab, “Yah... Tapi gue nggak beranggapan sama
dengan mereka! Kak, lo cewek yang hebat dan pintar, dan meskipun lo dibilang aneh,
itu diri lo sendiri! Lo harus bangga sama diri sendiri!”
Kakakku membelalak tak percaya mendengarku mengatakan semua itu.
Demikian juga aku.
Tapi aku tidak berhenti, karena kusadari aku turut marah atas apa yang mereka
lakukan pada kakak. “Lagipula kak, lo kan masih punya teman yang benar-benar baik,
kayak Nino dan Alin, mereka itu sahabat sejati yang nerima lo apa adanya! Jadi..
biarkan saja teman-teman lo yang lain itu!”
Mata kakak yang sebelumnya melebar sekarang jadi agak berkaca-kaca.
Aku kaget. “He? Kakak nangis ya?”
“Ah nggak, nggak apa-apa!”, katanya ceria, seperti sudah kembali pada
dirinya yang dulu. “Iya, Yogi benar! Rara harusnya gak peduli sama mereka, dan jadi
diri Rara sendiri! Makasih ya Yogi!”
Aku mengangguk atas kata-katanya, namun sedetik kemudian aku merasa
malu.
Aku munafik.
Sebenarnya aku juga sering kesal padanya. Sering menyesali kenapa dia harus
menjadi kakakku. Dan kadang-kadang aku berharap dia tidak begitu. Tidak menjadi
dirinya yang ceria, bawel, dan segalanya itu.
Tapi mendengar kata-kata kakakku tadi, aku juga menyadari dia tidak
bermaksud seperti itu. Dia tidak pernah bermaksud menyakiti hatiku. Dia hanya
menjadi dirinya sendiri. Yang mana mungkin bukan hal yang baik juga. Tapi memang
dirinya seperti itu. Dan seharusnya tidak akan berubah.
Mungkin aku harus belajar untuk lebih mengerti.
Setelah itu Nino datang ke rumah untuk meminjam PR kakak. Dan ketika
melihatku ia (yang sama premannya dengan dirinya ketika SMP) memberikan sapaan
khasnya, “Heh! Awas lo kalau coba dekat-dekat Nadia!”
Dan aku mulai merasa kesal lagi dengan kakak.
***
Aku berumur empat belas tahun, kakakku berumur delapan belas tahun.
Akhirnya dia mendapatkan beasiswa itu, dan berangkat ke Jakarta, terpisah
beberapa ratus kilometer dari kami.
Menuju Fakultas Kedokteran di Universitas negeri nomor satu di Indonesia.
Sekarang tidak ada lagi ayah, ibu, dan aku disampingnya.
Tidak ada Nino dan Alin juga.
Aku hanya berharap, dia menjalani kehidupannya disana dengan bahagia.
Dan tidak ada yang menyakitinya seperti dulu.
***
Aku berumur lima belas tahun, kakakku berumur sembilan belas tahun.
Aku tidak bertemu dengannya hampir setahun, karena terakhir kali dia pulang
adalah ketika Idul Fitri, setelah itu, bahkan saat libur semesteran dan ulang tahun
kami ia tidak kembali. Katanya, urusan di kampus.
Ayah bertanya padaku tentang cita-citaku nanti.
Aku memikirkan keputusan yang pernah kuambil beberapa tahun lalu, tentang
karir di bidang sosial itu. Itu adalah keputusan yang terburu-buru. Dan sebenarnya
ketika itu (aku masih 11 tahun, kelas lima SD) minatku seimbang pada bidang sains
maupun sosial. Tapi determinasiku yang tidak ingin lagi dibanding-bandingkan
dengan kakakku yang memang master di bidang sains, mulai mengarahkanku untuk
lebih mendalami pelajaran-pelajaran sosial.
Dan lama-kelamaan, aku menjadi jatuh cinta di bidang tersebut, terutama
jurnalistik. Aku suka menulis. Aku suka membaca. Dan aku tipe orang yang lebih
mudah menuliskan sesuatu daripada membicarakannya secara oral (ingat kasus
Nadia).
Aku menjawab, “Yogi ingin jadi wartawan, yah.”
Ayah dan Ibu tersenyum.
***
Aku berumur enam belas tahun, kakakku berumur dua puluh tahun.
Pada hari ulang tahun kami, kakak pulang ke rumah.
Dan ayah dan ibu mengatakan pada kami bahwa sesungguhnya kakak
bukanlah anak kandung mereka.
Aku terkejut hingga rasanya jantungku loncat ke tenggorokan.
Anehnya kakak menerima semua itu dengan tenang. Tahun-tahun di Jakarta
telah membentuknya menjadi seorang pribadi yang lebih tenang. Terlalu tenang
sampai-sampai aku tidak mengenalinya.
“Rara sudah tahu kok yah, bu,”
Aku bicara padanya setelah makan malam.
“Kak... yang barusan itu..?”
Ia tersenyum padaku, kemudian mengangguk.
Kakak mengetahui itu semua dari seorang dosennya di kampus, yang
merupakan teman dari ibu kandung kakak. Ia adalah seorang dokter, dan kebetulan ia
juga menempuh pendidikan dokter di universitas yang sama dengan kakak.
Tampaknya, ayah kakak, suami wanita itu meninggal dalam suatu kecelakaan dan
karena terkejut, ia melahirkan lebih cepat dan beberapa hari setelah kelahiran, ia
meninggal. Ayah telah mengenal dokter itu sejak lama, dan memutuskan merawat
kakak bersama ibu.
“Awalnya aku kaget, dan merasa terluka, tapi mengetahui segalanya amatlah
melegakan. Aku sudah penasaran sejak SMA, ketika aku melakukan tes golongan
darah, yang kemudian membuktikan aku tidak mungkin anak kandung ayah dan ibu.”
Aku merasa tidak mampu berkata-kata.
“Tapi.. tapi kenapa lo nggak bilang, atau tanya sama ayah dan ibu?”
Lagi-lagi ia tersenyum, tapi senyumnya berbeda dengan senyum-senyumnya
yang sebelumnya. Seperti sebuah senyum yang benar-benar lepas dari hatinya, bukan
sekedar senyum kegembiraan atau ramah tamah yang biasa ia tunjukkan.
“Karena aku tahu, mereka akan bilang padaku suatu saat. Aku hanya perlu
menunggu.”
Saat itu, melihat wajahnya yang bercahaya, aku tahu kakak telah menemukan
apa yang dicarinya selama ini.
Dan tiba-tiba aku merasa sedikit pedih.
Ia bukan kakakku. Kami tidak sedarah. Setelah segala yang telah kami
lakukan bersama. Setelah segala yang ia lakukan padaku, dan aku lakukan padanya
Aku tidak tahu harus merespon apa, jadi kukatakan, “Kak... apa lo bahagia?”
“Bahagia? Tentu,” jawabnya cepat. “Dan yang paling bikin aku bahagia, aku
dibesarkan oleh ayah dan ibu, dan tumbuh besar bersama kamu. Adik paling hebat
sedunia.”.
Aku memandangnya bingung. Ia balas menatapku.
“Maaf ya, kalau aku selalu buat repot kamu. Aku nggak pernah bisa jadi kakak
yang baik, malah selalu buat kamu kesal. Dan ternyata kita gak sedarah, aku.. aku
minta maaf atas segala kekacauan yang udah aku bikin.”
“Apa?”
“Ulang tahun kita sama, bahkan wajah kita pun agak mirip, sepertinya, kita
memang ditakdirkan menjadi kakak-adik. Tapi sifat kita benar-benar berbeda, dan aku
sadar, kamu yang selalu beradaptasi dengan aku, sementara aku selalu bertindak tanpa
berpikir yang akhirnya menyulitkan kamu.”
Kakak terlihat sangat emosional ketika melanjutkan kata-katanya.
“Yogi, untuk semuanya, aku ucapkan terima kasih, dan sekaligus maaf. Aku
minta maaf.”
“Apa?”, entah keberapa kali aku mengulang kata ini. Aku tidak percaya
dengan apa yang kudengar. Kutatap ia lekat-lekat. Ia juga menatapku. Bisa kulihat
bahwa ia serius dengan apa yang ia katakan. Ia merasa bersalah padaku.
“Kak. Jangan bicara seperti itu lagi. Lo... jangan pernah minta maaf lagi.”,
akhirnya tenggorokanku mampu mengeluarkan kata-kata. “Lo adalah kakak gue, dan
repot-ngerepotin itu biasa untuk kakak-adik.”
Aku melanjutkan, dengan agak tercekat, “ Dan… kalau bukan karena lo ada
sebagai kakak gue, gue gak akan jadi diri gue yang sekarang ini.”
Tenggorokanku seakan tersumbat, masih banyak yang ingin kukatakan namun
tak satu kata pun yang mampu kuucapkan. Disaat aku berjuang mengeluarkan suara
diantara bulir-bulir air yang menggenang di mata dan tenggorokanku, kakak memeluk
bahuku.
“Terima kasih, Yogi. Terima kasih…”
Aku merasakan bahuku basah dengan air mata. Kami sama-sama menangis
malam itu.
***
Sekarang aku berumur dua puluh tahun, kakakku berumur dua puluh empat
tahun.
Kini aku menempuh kuliah di Universitas yang sama dengan kakak, Fakultas
Ilmu Komunikasi, jurusan Jurnalistik. Kakakku akan disumpah dokter bulan depan,
dan keluarga kami sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan syukuran yang akan
diselenggarakan atas kelulusannya. Terutama ibu yang membongkar barang-barang di
rumah dan membuat rumah kami seperti kapal pecah.
Pada saat itulah aku secara kebetulan menemukan karangan kakakku yang ia
tulis tujuh belas tahun lalu.
Aku sudah pernah membacanya ketika SMP, dan yang kurasakan setelahnya
adalah rasa malu. Sekarang aku membacanya lagi, dan aku tersenyum.
Pada baris terakhir karangannya tertulis, “.....Meskipun dia nakal, tapi Yogi
tetap adikku yang kusayang. Dan dia adalah hadiah ulang tahun yang paling indah
yang pernah ada!”
***
Aku memiliki seorang kakak perempuan.
Dia memang agak aneh dan suka membuat masalah, tapi mau bagaimana lagi?
Dia adalah kakakku.
untuk adikku yang ada di surga
Karangan : Tiara Nien Paramita
You might also like
- Adik Sepupu Ku Terangsang Berat Ketika Kuminta Dia Memijat Tubuh KuDocument4 pagesAdik Sepupu Ku Terangsang Berat Ketika Kuminta Dia Memijat Tubuh KuSentinel JuniorNo ratings yet
- Pengalaman Sex Dengan Teman KerjaDocument6 pagesPengalaman Sex Dengan Teman KerjacumplunglowoNo ratings yet
- Eksebisi Dengan KakakDocument7 pagesEksebisi Dengan Kakakbrianstreck0% (1)
- Bibi LintikDocument15 pagesBibi LintikDefri Rahman100% (1)
- Episode 2 - Perkenalan Istri Andri, Bella 1Document4 pagesEpisode 2 - Perkenalan Istri Andri, Bella 1DidimencobauntuksetiaSangatingindimengertiTanpainginmenyakitiNo ratings yet
- Karena Nila SetitikDocument31 pagesKarena Nila Setitikdanny adrianNo ratings yet
- BabeDocument14 pagesBabeRosa LindaNo ratings yet
- JJJJDocument7 pagesJJJJFaisal Wijaya Kusuma0% (1)
- Ibu Tiri Syarat PesugihanDocument6 pagesIbu Tiri Syarat PesugihanShared Mail50% (2)
- StoryDocument45 pagesStoryDian pebriansyahNo ratings yet
- Cerita Ngentot PacarDocument4 pagesCerita Ngentot PacarmongkiNo ratings yet
- Cerita Hot - ABG Semok 17tahunDocument1 pageCerita Hot - ABG Semok 17tahunErick FathoniNo ratings yet
- ML di Toilet KampusDocument6 pagesML di Toilet KampusVingga DayskaNo ratings yet
- Aku Anggie Sonya Dan AdiknyaDocument5 pagesAku Anggie Sonya Dan Adiknya20051982No ratings yet
- 1 4925231464397668756Document8 pages1 4925231464397668756Youtube PremiumNo ratings yet
- BERMIMPI KE JAKARTADocument6 pagesBERMIMPI KE JAKARTAdanny adrianNo ratings yet
- Story 1Document4 pagesStory 1Naufal Faruq0% (1)
- Xtra Stories of Making Love Out of Nothing at AllDocument309 pagesXtra Stories of Making Love Out of Nothing at AllJacopoNo ratings yet
- Bakal - Adik IparDocument7 pagesBakal - Adik IparHmm HmmmNo ratings yet
- MDTKDocument9 pagesMDTKDidimencobauntuksetiaSangatingindimengertiTanpainginmenyakitiNo ratings yet
- Antara AkuDocument8 pagesAntara AkuAndy Wong Boegis100% (1)
- Berkeringat Saat PanasDocument9 pagesBerkeringat Saat PanasMuhammad Riandy Lukman TanjungNo ratings yet
- BERSAMADocument10 pagesBERSAMAshuca2cat50% (2)
- Mengalir Bagaikan AirDocument55 pagesMengalir Bagaikan AirHeepy Hariyadi100% (1)
- Namaku Evelyn LinDocument7 pagesNamaku Evelyn LinIan WaeNo ratings yet
- UntitledDocument34 pagesUntitledmikeshawn_imanNo ratings yet
- Cerita 1Document5 pagesCerita 1JimauNo ratings yet
- 3 Tahun Tunggu HamilDocument25 pages3 Tahun Tunggu HamilArie Suryanto ZanettiNo ratings yet
- Cerita DewasaDocument1 pageCerita DewasaДжимми ДжиммиNo ratings yet
- Greta, Cinta Ku Yang KembaliDocument4 pagesGreta, Cinta Ku Yang KembaliTjap TjoeanNo ratings yet
- CerpenDocument4 pagesCerpennurilNo ratings yet
- Saya mengerti keinginan Anda untuk berbagi pengalaman pribadi, namun beberapa detail dalam narasi tersebut kurang sesuai. Mari kita bahas topik lain yang lebih konstruktifDocument6 pagesSaya mengerti keinginan Anda untuk berbagi pengalaman pribadi, namun beberapa detail dalam narasi tersebut kurang sesuai. Mari kita bahas topik lain yang lebih konstruktifDidimencobauntuksetiaSangatingindimengertiTanpainginmenyakiti0% (1)
- SEXISME_DALAM_KELUARGADocument7 pagesSEXISME_DALAM_KELUARGAJuniorNo ratings yet
- Bu Dosen Dan PembantunyaDocument4 pagesBu Dosen Dan PembantunyaShared MailNo ratings yet
- Wanita Kesepian 2Document4 pagesWanita Kesepian 220051982No ratings yet
- Aku Bersetubuh Dengan Hewan SingaDocument13 pagesAku Bersetubuh Dengan Hewan SingaMas AndiNo ratings yet
- MENGINTIPDocument28 pagesMENGINTIPAjiedhika PratamaNo ratings yet
- Turun TemurunDocument7 pagesTurun TemurunIko Sandy28No ratings yet
- Xtra Stories (Yuli) Making Love Out of Nothing at AllDocument72 pagesXtra Stories (Yuli) Making Love Out of Nothing at AlldariawanNo ratings yet
- Tawaran Kehangatan Dari Istri Kakak IparDocument90 pagesTawaran Kehangatan Dari Istri Kakak IparWong BagoesNo ratings yet
- Story 3Document15 pagesStory 3Nuril FrangkyNo ratings yet
- Cerpen Kakakku NakalDocument4 pagesCerpen Kakakku NakalNurAzliNo ratings yet
- Berawal Dari Celana Dalam VitaDocument5 pagesBerawal Dari Celana Dalam VitaShared Mail100% (1)
- Daud Dan SitiDocument4 pagesDaud Dan SitiTjap TjoeanNo ratings yet
- LKTCPDocument14 pagesLKTCPnoldy RisaNo ratings yet
- Mengasuh YarmiDocument7 pagesMengasuh Yarmidanny adrianNo ratings yet
- Terjerat Pergaulan BebasDocument6 pagesTerjerat Pergaulan BebasDefri RahmanNo ratings yet
- 21 RomanceDocument180 pages21 RomanceEddie50% (2)
- IbuDocument9 pagesIbuMohsan AlkuriNo ratings yet
- Aku Selingkuh Dengan Adik PacarkuDocument5 pagesAku Selingkuh Dengan Adik Pacarkubebas baeNo ratings yet
- MEMEK MBAK AMBARDocument5 pagesMEMEK MBAK AMBARDefri RahmanNo ratings yet
- Penjaga Kampus Dengan MAhasiswiDocument8 pagesPenjaga Kampus Dengan MAhasiswidanny adrianNo ratings yet
- Pondok UsangDocument4 pagesPondok UsangSS Suria0% (1)
- Bibiku KorbankuDocument12 pagesBibiku Korbankudanny adrianNo ratings yet
- Cerita Gadis Abg HotDocument2 pagesCerita Gadis Abg HotErick Fathoni100% (1)
- Per Ken AlanDocument93 pagesPer Ken Alanucok santosaNo ratings yet