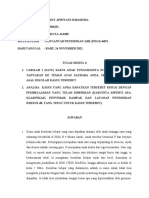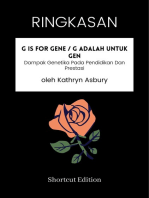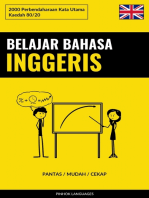Professional Documents
Culture Documents
Hubungan Guru dan Orang Tua
Uploaded by
Hendro MartonoOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Hubungan Guru dan Orang Tua
Uploaded by
Hendro MartonoCopyright:
Available Formats
Anak di antara Guru dan Orang Tua Oleh Hendro Martono Pada suatu hari anak saya yang
baru duduk di kelas tiga sekolah dasar mengajukan protes karena hasil pekerjaan rumah (PR) yang dikerjakan semalam hanya mendapat nilai 6,9. Saya dipersalahkan dan tampak sekali si anak menuntut pertanggungjawaban orang tua yang telah membimbing belajarnya. Usut punya usut, banyak jawaban yang setelah dicocokkan di sekolah ternyata salah. Sebagai orang tua yang kebetulan juga berprofesi sebagai guru- saya merasa perlu untuk meneliti kembali pekerjaan tersebut. Pada materi soal pelajaran bahasa daerah (bahasa Jawa) terdapat perintah Ukaraukara ing ngisor iki urutna dadi crita kang becik! (Urutkanlah kalimat-kalimat di bawah ini sehingga menjadi wacana yang baik). Pada wacana pertama terdapat urutan kalimat (jika dialihkan ke dalam bahasa Indonesia) : (a) Rumahnya di kota Semarang; (b) Kapalnya besarbesar sedang memuat barang beraneka ragam; (c) Ketika libur panjang aku pergi ke tempat nenek; (d) Di sana aku melihat pelabuhan Tanjung Mas. Gagasan utama pada wacana di atas cukup jelas sehingga urutan kalimatnya dengan cukup mudah disusun oleh anak saya dengan urut-urutan kalimat (c); (a); (d) dan (b). Hasil pencocokan di sekolah menunjukkan jawaban ini benar. Akan tetapi, anak saya kemudian ternyata saya juga- keliru menjawab pada waktu menggarap soal kedua dengan materi kalimat : (a) Kebunnya dibuat berpetak-petak; (b) Tanaman di kebun itu beraneka warna; (c) Setiap hari tanaman itu dipelihara; dan (d) Kebun Pak Suta ditanami apotek hidup, buahbuahan dan sayur-sayuran (Lihat Parkin dkk., Wibawa : Widya Basa Jawa Jilid 3, Solo : PT Tri Manunggal Kurniajaya, hal. 19). Berdasarkan telaah atas hubungan antara kalimat utama dan kalimat penjelas, saya menyarankan jawaban dengan urut-urutan kalimat (d); (a); (b); dan (c). Apa yang terjadi? Hasil pencocokkan dengan guru di sekolah dasar menunjukkan jawaban anak saya tersebut
ternyata salah. Menurut versi guru, susunan jawaban yang benar adalah berturut-turut kalimat (a); (d); (c); dan (b). Inilah yang menjadi bencana bagi saya karena diomeli oleh anak. Sebagai orang tua yang telah lama tidak belajar tata-bahasa bahasa Jawa terakhir kali belajar bahasa Jawa ketika masih duduk di Sekolah Pendidikan Guru, tamat tahun 1982- saya merasa tidak memiliki kompetensi lagi tentang bahasa Jawa. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman sebagai guru mata pelajaran, saya memberanikan diri memberikan tanggapan sebagai berikut. Pertama, pada wacana kedua itu jika kalimatnya dimulai dari kalimat (a) maka hubungan antarkalimatnya kurang inheren. Sebaliknya, jika paragraf itu dimulai dari kalimat (d), kalimat utamanya dapat dirujuk pada subjek : Pak Suta, sementara kalimat (a) tidak jelas menyebutkan subjek kalimat. Atau, subjek kalimat (a) merupakan kata ganti empunya yang mestinya tidak boleh mendahului subjek pada kalimat (d). Di samping itu, sebenarnya kalimat (a) dapat disarankan perbaikannya agar susunannya lebih baik, yaitu Kebun Pak Sutadan seterusnya sehingga subjeknya jelas. Akan tetapi, menempatkan kalimat (a) pada urutan pertama menurut pendapat saya tetap saja tidak mempunyai hubungan yang inheren dengan ketiga kalimat lain. Kedua, hubungan dalam urutan kalimat (b) dan (d) sebenarnya rancu karena akan berebut urutan susunan di dalam paragraf. Kedua kalimat itu akan lebih baik jika digabungkan menjadi Tanaman di kebun Pak Suta beraneka ragam seperti : apotek hidup, buah-buahan dan sayur-sayuran sehingga perlu ditambah satu kalimat baru. Berdasarkan kemungkinan ini, tampaknya contoh kalimat pada buku pelajaran itu yang justru bermasalah. *** Berdasarkan kasus tersebut beberapa pelajaran berharga dapat dipetik. Pertama, perbedaan pendapat antara guru dan orang tua di satu pihak akan memengaruhi kredibilitas keduanya; dan di lain pihak justru akan membingungkan anak. Jika pendapat guru benar,
anak akan cenderung melecehkan kredibilitas orang tua. Sebaliknya, anak tidak mudah percaya pada pendapat orang tua meskipun pendapat itu benar. Dalam banyak kasus, anak cenderung lebih tunduk pada otoritas guru di dalam kelas daripada orang tua di rumah, apa pun pendapat orang tua dan apa pun pendapat guru. Anak, dengan demikian seperti berada dalam hubungan ketegangan antara otoritas guru dan orang tua. Jika pendapat guru di kelas benar ini tidak menjadi masalah. Akan sangat merepotkan bila ternyata pendapat guru salah sementara si anak tidak mau atau tidak rela mengakui kesalahan itu. Kedua, ada kebutuhan mendesak agar kedua belah pihak, yaitu guru dan orang tua untuk terus belajar guna memutakhirkan pengetahuan yang dimiliki, karena pengetahuan di luar dirinya terus berkembang. Profesi saya sebagai guru mata pelajaran di SLTA terbukti sama sekali kurang relevan ketika membimbing anak yang masih duduk di sekolah dasar. Pengetahuan yang pernah diperoleh semasa di sekolah dasar pun kini sangat tertinggal. Diperlukan kesediaan orang tua agar mau belajar, persis seperti yang dilakukan oleh anaknya. Jika anak sedang belajar Matematika, misalnya, semestinya orang tua juga memahami materi yang tengah dipelajari anaknya. Mengikuti anjuran Andrias Harefa (2001), orang tua pada dasarnya merupakan guru yang pertama dikenal oleh anak, dan karena itu tugas orang tua tidak selesai begitu saja ketika menyerahkan pendidikan anaknya di sekolah. Sebaliknya, guru pada dasarnya merupakan orang tua di sekolah yang bertugas menggantikan peran orang tua di dalam keluarga. Tugas mendidik, membimbing, mengajar dan melatih dengan demikian hendaknya tidak terdistorsi oleh buku pelajaran yang kebetulan bukan buku paket- dengan memperlakukannya sebagai buku suci yang kedap kritik. Maksudnya, sebelum membelajarkan materi pada anak seyogyanya buku itu ditelaah kebenaran substansialnya agar tidak menimbulkan kebingungan. Pada kasus anak saya, ini sebenarnya bukan yang pertama. Untuk mata pelajaran yang sama (bahasa Jawa), sang guru ini pernah memberikan pengetahuan yang menyesatkan 3
karena mengartikan Kaline lagi bena (Sungainya sedang banjir) dengan pengertian Kaline lagi asat (Sungainya sedang mengering). Ini menunjukkan contradicto in terminis yang jika tidak dibetulkan akan menyesatkan pengetahuan anak. Ketiga, ada kesan masih kuatnya ketergantungan guru terhadap buku-buku pelajaran atau yang sejenis seperti Lembar Kerja Siswa (LKS). Di samping nuansa komersial yang selalu menimbulkan kontroversi pada setiap awal tahun pelajaran, keberadaan sejumlah buku dan LKS untuk setiap mata pelajaran sangat memberatkan anak. Di samping buku paket, guru biasanya menggunakan buku terbitan Jakarta dan LKS-LKS terbitan lokal. Meskipun maksudnya keberadaan buku-buku itu untuk memaksa anak belajar, jika substansinya langsung diajarkan tanpa ditelaah lebih dahulu akan menimbulkan kasus seperti di atas. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi guru adalah keberanian untuk melepaskan ketergantungan ini dengan konsekuensi kehilangan keuntungan finansial. Akan tetapi, akan ada keuntungan immateri bila guru sanggup menyusun sendiri bahan ajarnya. Ada alasan menarik yang perlu dikemukakan, yaitu dengan berlakunya kurikulum 2004 setidaknya seperti yang termuat pada kurikulum SMK 2004- yang menganjurkan penggunaan modul seharusnya dapat memaksa setiap guru untuk membuat modul. Dikaitkan dengan keputusan rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat oleh kabinet baru yang merekomendasikan penggunaan buku pelajaran selama lima tahun (Kompas, 24/10), keharusan setiap guru untuk menyusun modul benar-benar harus mendapat perhatian. Konsekuensi dari rekomendasi tersebut, jika penyikapan guru terhadap buku pelajaran yang digunakan tetap saja seperti pada kasus di atas, dapat dibayangkan betapa repot anak dan orang tua dalam menelaah substansi pelajaran. Akan terjadi selama lima tahun, anak dan orang tua dibingungkan oleh isi buku yang kurang sahih, sementara guru memperlakukan teks buku sebagai sesuatu yang final. ***
Jika kasus seperti yang dialami oleh anak saya ini dikemukakan di sini, sesungguhnya itu tidak berpretensi untuk mengolok-olok kinerja guru, tetapi untuk saling menyadarkan akan peran guru di kelas dan orang tua di rumah. Jika guru dan orang tua dapat membangun sinergi dengan terus memperbaiki kualitas peran dan fungsi masing-masing diharapkan anak tidak lagi berada dalam tarikan ketegangan antara otoritas guru dan orang tua. Sebaliknya, anak justru akan mendapatkan iklim belajar yang sehat karena baik guru maupun orang tua memiliki kompetensi yang sepadan dalam membelajarkan anak. Untuk membangun sinergi yang positif itu masing-masing pihak harus saling terbuka terhadap kebenaran yang datang dari mana pun. Guru tidak alergi terhadap kritik orang tua, begitu pula orang tua. Ini dapat dicapai pada saat kedua belah pihak memiliki taraf kompetensi yang seimbang.
You might also like
- Membantu Anak Kelas Satu SD BelajarDocument3 pagesMembantu Anak Kelas Satu SD BelajaraytihdaNo ratings yet
- Artikel Communicative Language LearningDocument42 pagesArtikel Communicative Language LearningReza Novianda0% (1)
- Refleksi KelasDocument4 pagesRefleksi KelasOswindra HermanuNo ratings yet
- Isi Sambutan Wali KelasDocument7 pagesIsi Sambutan Wali KelasAnton Timur100% (1)
- Artikel BebasDocument3 pagesArtikel BebasMIN 7 BLITARNo ratings yet
- Contoh Soal TAPDocument13 pagesContoh Soal TAPMichaella 710No ratings yet
- Tentang BimbelDocument8 pagesTentang Bimbelmilla36No ratings yet
- Contoh KasusDocument2 pagesContoh KasusSuns InformatikaNo ratings yet
- Rangkuman Modul 10Document16 pagesRangkuman Modul 10Yayan IndraNo ratings yet
- Kasus ADocument4 pagesKasus AHadi Kurniawan Sujatman50% (2)
- LAPORAN OBSERVASI BIMBINGAN DAN KONSELING (Zainagnes Almawardhani)Document15 pagesLAPORAN OBSERVASI BIMBINGAN DAN KONSELING (Zainagnes Almawardhani)zainagnes almawardhaniNo ratings yet
- Jawaban Soal Esiy Guru Pengerak JumaliDocument11 pagesJawaban Soal Esiy Guru Pengerak JumaliadhityaaongNo ratings yet
- MEMBOLOS SEKOLAHDocument14 pagesMEMBOLOS SEKOLAHajieko putrosantosoNo ratings yet
- Tugas Tuweb Ii PKP - Cindy DamayantiDocument5 pagesTugas Tuweb Ii PKP - Cindy DamayantiCindy DamayantiNo ratings yet
- PendidikanDocument11 pagesPendidikanedwin SahidNo ratings yet
- Tugas Akhir ProgramDocument4 pagesTugas Akhir ProgramRofie' AbbdulNo ratings yet
- MEMPERKASAKAN LITERASI MURID PEMULIHANDocument27 pagesMEMPERKASAKAN LITERASI MURID PEMULIHANTcer ZazaNo ratings yet
- Adab Dengan Guru Makin TerhakisDocument5 pagesAdab Dengan Guru Makin TerhakisFaisal MahmodNo ratings yet
- Diskusi 4 PKRDocument2 pagesDiskusi 4 PKRSri MaritaNo ratings yet
- Guru Profesional Lebih Mendidik Daripada MengajarDocument6 pagesGuru Profesional Lebih Mendidik Daripada MengajarSITI HAFSAH INTAN SARINo ratings yet
- JWBN Esay DesviDocument8 pagesJWBN Esay Desvidesvist28No ratings yet
- Abstract: Covid-19 Sudah Tidak Asing Lagi Di Mata OrangDocument10 pagesAbstract: Covid-19 Sudah Tidak Asing Lagi Di Mata OrangNysa AisihiteruNo ratings yet
- Makalah Fenomena HomeschoolingDocument14 pagesMakalah Fenomena HomeschoolingSyafira MaulidaNo ratings yet
- Wa0001.Document20 pagesWa0001.Tirsya LuturmasNo ratings yet
- Kisi-Kisi Bahasa Inggris Sastra Pertemuan 2Document12 pagesKisi-Kisi Bahasa Inggris Sastra Pertemuan 2debby Tri handayaniNo ratings yet
- Pidato Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Pada Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019Document4 pagesPidato Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Pada Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019Didik FirmansyahNo ratings yet
- Studi KasusDocument12 pagesStudi KasusAlif Rohmah67% (3)
- Kurikulum SMP PangudiDocument12 pagesKurikulum SMP PangudiMargaretha WendaNo ratings yet
- Debat PendidikanDocument7 pagesDebat PendidikanRIZKA MAULANANo ratings yet
- Masalah Belajar Siswa SDDocument11 pagesMasalah Belajar Siswa SDPutri SalmaNo ratings yet
- Skripsi Trio Dika Kurniawan Mahasiswa PGSD Universitas JambiDocument10 pagesSkripsi Trio Dika Kurniawan Mahasiswa PGSD Universitas JambiDikaPujakesumaNo ratings yet
- Tap JhoDocument14 pagesTap JhoNuning MutiaNo ratings yet
- Punca Dan Cara Mengatasi Masalah Pengajaran Bahasa Inggeris Di SekolahDocument8 pagesPunca Dan Cara Mengatasi Masalah Pengajaran Bahasa Inggeris Di Sekolahcik petir82% (17)
- Pertemuan 2, TAP-Masalah Studi Kasus Dalam Pembelajaran MatematikaDocument18 pagesPertemuan 2, TAP-Masalah Studi Kasus Dalam Pembelajaran MatematikaHalbiNo ratings yet
- PEMBELAJARAN SAINTIFIKDocument15 pagesPEMBELAJARAN SAINTIFIKMuntoha Nurwahid100% (1)
- 2A Rahma Isnaini Studi KasusDocument5 pages2A Rahma Isnaini Studi KasusSuhermanNo ratings yet
- Contoh Soal Tap PGSD U1Document5 pagesContoh Soal Tap PGSD U1irfanNo ratings yet
- TT2 PPD - Pesta Melani - 856063862Document4 pagesTT2 PPD - Pesta Melani - 856063862M SNo ratings yet
- Tugas Sesi 6 Modul 6 - Resky Apriyani Simamora - 856583291Document9 pagesTugas Sesi 6 Modul 6 - Resky Apriyani Simamora - 856583291Resky Apriani simamoraNo ratings yet
- Tugas PTK Uma DaDocument5 pagesTugas PTK Uma DaFadhil MahmudiNo ratings yet
- Pendidikan Merupakan Suatu Perkara Pokok Yang Menjadi Kebutuhan ManusiaDocument3 pagesPendidikan Merupakan Suatu Perkara Pokok Yang Menjadi Kebutuhan ManusiaReni AnggrainiNo ratings yet
- Contoh Studi Kasus SDDocument6 pagesContoh Studi Kasus SDAninda Mawar Intanuari100% (8)
- Studi KasusDocument13 pagesStudi KasusSilvianingsiNo ratings yet
- Tugas Tutorial 1 TAPDocument11 pagesTugas Tutorial 1 TAPKomang Sri AntiniNo ratings yet
- Artikel Permasalahan Di Lingkungan Sekolah DasarDocument1 pageArtikel Permasalahan Di Lingkungan Sekolah DasarPanjiRizalulFatah100% (2)
- SD HomeschoolingDocument6 pagesSD HomeschoolingFany Fiverz CloudsNo ratings yet
- Pengaruh Pola Asuh Dalam Lingkungan Keluarga Terhadap Perilaku Anak Remaja Di SekolahDocument35 pagesPengaruh Pola Asuh Dalam Lingkungan Keluarga Terhadap Perilaku Anak Remaja Di Sekolahanggi fathmaNo ratings yet
- tt2 pkr 855881094 awali nurDocument5 pagestt2 pkr 855881094 awali nurAreza MisbahNo ratings yet
- RANCANGAN PEMBELAJARANDocument3 pagesRANCANGAN PEMBELAJARANEmon De Rawi100% (2)
- B.indo GefirDocument16 pagesB.indo GefirtayuNo ratings yet
- (152210029) Nur Ananda Sy. UAS Psikologi Pendidikan (2) - 1Document8 pages(152210029) Nur Ananda Sy. UAS Psikologi Pendidikan (2) - 1Tarisya RidhatiNo ratings yet
- Punca Dan Cara Mengatasi Masalah Pengajaran Bahasa Inggeris Di SekolahDocument8 pagesPunca Dan Cara Mengatasi Masalah Pengajaran Bahasa Inggeris Di SekolahArun NarayananNo ratings yet
- Tugas 3 AbkDocument5 pagesTugas 3 AbkMuis Aji AlqorniNo ratings yet
- BIDocument16 pagesBIZahiruddin ZahrudinNo ratings yet
- TAP S1 PGSD UTDocument7 pagesTAP S1 PGSD UT412 ChannelNo ratings yet
- Contoh Soal TAP S1 PGSD UTDocument7 pagesContoh Soal TAP S1 PGSD UT412 Channel100% (1)
- RINGKASAN: G Is For Gene / G Adalah Untuk Gen: Dampak Genetika Pada Pendidikan Dan Prestasi Oleh Kathryn AsburyFrom EverandRINGKASAN: G Is For Gene / G Adalah Untuk Gen: Dampak Genetika Pada Pendidikan Dan Prestasi Oleh Kathryn AsburyNo ratings yet
- Belajar Bahasa Inggeris - Pantas / Mudah / Cekap: 2000 Perbendaharaan Kata UtamaFrom EverandBelajar Bahasa Inggeris - Pantas / Mudah / Cekap: 2000 Perbendaharaan Kata UtamaNo ratings yet
- Angket Buku 2011Document2 pagesAngket Buku 2011Hendro MartonoNo ratings yet
- Dimensi Kepetingan Publik Dalam Kerjasama AseanDocument7 pagesDimensi Kepetingan Publik Dalam Kerjasama AseanHendro MartonoNo ratings yet
- Proposal Tesis - Penelitian Deskriptif MarkhamahDocument31 pagesProposal Tesis - Penelitian Deskriptif MarkhamahHendro MartonoNo ratings yet
- UntitledDocument1 pageUntitledHendro MartonoNo ratings yet