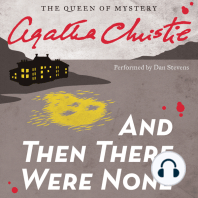Professional Documents
Culture Documents
Memonopoli Perdagangan
Uploaded by
Aly MuchamadOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Memonopoli Perdagangan
Uploaded by
Aly MuchamadCopyright:
Available Formats
Hak istimewa voc: 1.Memonopoli perdagangan 2. Memiliki pengadilan dan tentara sendiri 3.
Menguasai dan mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di daerah monopoli perdagangan 4. Membuat uang sendiri 5. Mendirikan benteng pertahanan 6. Mengangkat/ memberhentikan penguasa setempat
1. Banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi. 2. Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan contoh perang melawan Hasanuddin dari Gowa. 3. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. 4. Pembayaran Devident (keuntungan) bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan. 5. Bertambahnya saingan dagang di Asia terutama Inggris dan Perancis. 6. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf 1795 yang demokratis dan liberal menganjurkan perdagangan bebas. Akhirnya VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal serta daerah kekuasaan di Indonesia pelayaran hongi untuk memberantas penyelundupan. Tindakan yang dilakukan VOC adalah merampas setiap kapal penduduk yang menjual langsung rempah-rempah kepada pedagang asing seperti Inggris, Perancis dan Denmark. Hal ini banyak dijumpai di pelabuhan bebas Makasar. Hongi adalah nama jenis perahu di Maluku yang bentuknya panjang dipakai untuk patroli laut Belanda yang didayung secara paksa oleh penduduk setempat
Cultuurstelsel (atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai Tanam Paksa) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Tanam Paksa ini mulai dilaksanakan di Indonesia khususnya di Pulau Jawa pada tahun 1830, dan hal ini merupakan manifestasi dari forced specialization yang didasarkan pada analisis manfaat komparatif Ricardo oleh pihak penjajah. Spesialisasi tanam paksa ini dijalankan dengan cara pembiayaan brutal dalam bentuk kerja paksa atau mobilisasi paksa dan ini merupakan komersialisasi kolonial di sektor pertanian. Proses ini
mengakibatkan surplus ekonomi yang praktis tanpa modal pokok yang berarti, karena modal pokok dalam investasi tanam paksa ini adalah tenaga kerja petani kita di Pulau Jawa (Frank, 1981) Tenaga kerja yang diperas dengan pendapatan riil yang kecil menempatkan para petani menjadi tenaga kerja yang optimal bagi Belanda yang mana akhirnya proyek ini menciptakan strata sosial di dalam masyarakat dan menempatkan petani pada strata sosial bawah yang tidak sanggup memperbaiki dirinya sendiri apalagi untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Egbert de Vries (1931) atas kajiannya mengenai kasus kegiatan pertanian di Pasuruan yang menjadi contoh kehidupan petani pada waktu itu. Pada tahun 1926 Vries menggambarkan bahwa sebanyak 62,5% dari penduduk pedesaan Jawa tergolong sebagai lapisan miskin desa atau proletariat desa. Kelompok proletariat desa ini kemudian dalam sejarah investasi kolonial berikutnya, yaitu pembukaan perkebunan-perkebunan besar di Jawa dan Sumatra Timur setelah cultuurstelsel berakhir, menjadi sumber buruh murah bagi perkebunan-perkebunan besar ini. Pengiriman penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera mirip dengan pengiriman budak oleh kekuasaan kolonial Inggris ke West Indies untuk dipaksa bekerja di perkebunan-perkebunan gula disana. Surplus ekspor (sesudah dikurangi impor) sebagai hasil cultuurstelsel tercatat berjumlah 781 juta Gulden dalam periode 1840-1875 dan melonjak luar biasa ketika terjadi pembukaan perkebunanperkebunan besar di Jawa dan Sumatera, yaitu menjadi 3,3 milyar gulden dalam periode 1915-1920 (Hatta, 1972), namun demikian tanam paksa ini tidak memberikan kemakmuran bagi negara jajahannya. Kondisi kemiskinan dan penindasan sejak tanam paksa dan UU Agraria, ini mendapat kritik dari para kaum humanis Belanda. Seorang Asisten Residen di Lebak, Banten, Eduard Douwes Dekker mengarang buku Max Havelaar (1860). Dalam bukunya Douwes Dekker menggunakan nama samaran Multatuli. Dalam buku itu diceritakan kondisi masyarakat petani yang menderita akibat tekanan pejabat Hindia Belanda. Namun demikian usaha kaum liberal di negeri Belanda agar Tanam Paksa dihapuskan telah berhasil pada tahun 1870, dengan diberlakukannya UU Agraria, Agrarische Wet. Tetapi tujuan yang hendak dicapai oleh kaum liberal tidak hanya terbatas pada penghapusan Tanam Paksa. Mereka mempunyai tujuan lebih lanjut. Gerakan liberal di negeri Belanda dipelopori oleh para pengusaha swasta. Oleh karena itu kebebasan yang mereka perjuangkan terutama kebebasan di bidang ekonomi. Kaum liberal di negeri Belanda berpendapat bahwa seharusnya pemerintah jangan ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Mereka menghendaki agar kegiatan ekonomi ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah bertindak sebagai pelindung warga negara, menyediakan prasarana, menegakkan hukuman dan menjamin keamanan serta ketertiban. UU ini memperbolehkan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta menyewa lahan-lahan yang luas dengan jangka waktu paling lama 75 tahun, untuk ditanami tanaman keras seperti karet, teh, kopi, kelapa sawit, tarum (nila), atau untuk tanaman semusim seperti tebu dan tembakau dalam bentuk sewa jangka pendek.
Hatta (1972) melaporkan bahwa upah buruh perkebunan pada tahun 20an adalah sekitar 50 sen per harinya, sedangkan dividen yang diterima oleh pemegang saham modal swasta di negeri Belanda di Negeri Belanda rata-rata berada di atas 40%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikkan produktivitas buruh Indonesia bukan dinikmati oleh penduduk negeri ini, tetapi oleh para pemegang saham bangsa Belanda di Negeri Belanda. Contoh lain akibat penindasan dan diskriminasi secara ekonomi ini, Hatta juga melaporkan bahwa tahun 1925 pengeluaran pemerintah Hindia Belanda untuk anak-anak Indonesia hanya 32 sen per kapita. Sedangkan untuk pendidikan anak-anak Belanda di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda memberikan sebanyak 75 gulden per kapita atau lebih besar 225 kali lipat. Perbedaan yang mencolok ini mengakibatkan perbedaan kualitas pendidikan antara bumiputera dengan bangsa belanda. Dari sini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem ekonomi kolonial Belanda baik berupa tanam paksa ataupun pembukaan perkebunan oleh kaum pemodal-liberal Belanda di Indonesia bukan hanya mengobrak-ngabrik struktur ekonomi Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kemiskinan dan diskriminasi yang dialami oleh bangsa Indonesia
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5783)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionFrom EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (12941)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (3265)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19993)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2475)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionFrom EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2391)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19653)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationFrom EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationRating: 4 out of 5 stars4/5 (2385)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (2552)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6503)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)From EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9485)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseFrom EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseRating: 4 out of 5 stars4/5 (1103)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderFrom EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderRating: 4 out of 5 stars4/5 (5700)
- The Covenant of Water (Oprah's Book Club)From EverandThe Covenant of Water (Oprah's Book Club)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (516)




![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)