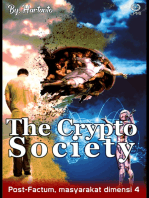Professional Documents
Culture Documents
Kritik Poskolonial
Uploaded by
Ken ArokOriginal Description:
Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Kritik Poskolonial
Uploaded by
Ken ArokCopyright:
Available Formats
Wacana Kolonial dan Kritik Poskolonialisme
Oleh Mujibur Rohman
Abstract
Colonial discourse is an ideological weapon to conquer the indigenous people. Its goal is to distinguish the colonizer and the colonized into two conflicting identities. Colonialism constructs the indigenous people in two ways. First, colonialism identifies the colonized by researches based on the rule of knowledge. Second, combining the structure of society they have created with the structure of the pre-colonial society. However, there are ambivalences and contradictions in the colonial discourses themself. Therefore, colonial discourse is not always successful. On the other hand, imitation made by the indigenous society to the colonial culture is a resistance strategy against colonialism, in which imitation is a form of mockery toward the culture and identity of the colonizer. Kata kunci: wacana kolonial, dekonstruksi, hibriditas
Pendahuluan Wa! Saja kira itoe ajer! Demikian bunyi headline iklan dalam surat kabar zaman kolonial Belanda, Sin Po, 19 Juli 1923. Iklan tersebut menampilkan gambar seorang pribumi memakai destar gaya Madura, lengkap dengan kostum lorengnya. Matanya terbelalak takjub sembari tangannya meraba cairan water witte petroleum Sheel. Entah dengan tujuan yang disengaja atau tidak, gambar tersebut memberikan imajinasi tertentu tentang masyarakat pribumi. Gambaran pribumi yang naif, yang tidak bisa membedakan antara air dan minyak. 1 Gambar dalam iklan tersebut menjadi bagian terkecil dari strategi kolonial untuk membentuk persepsi mengenai masyarakat pribumi. Persepsi, gambaran, atau bahkan stereotip tentang masyarakat pribumi ini disebarkan lewat berbagai media massa. Persepsi tersebut bertujuan untuk membelah masyarakat pribumi dan kolonial ke dalam dua kutub yang saling bertentangan. Pertentangan-pertentangan yang ingin dibangun yaitu, masyarakat pribumi adalah masyarakat yang irasional, naif, konyol, feminis, dan terbelakang. Persepsi tersebut dilawankan dengan Barat, yang menurut mereka sendiri, rasional, dewasa, maskulin, beradab, dan maju. Seluruh pengertian tentang beradab dan tidak beradab, baik secara implisit maupun secara eksplisit menjadi muatan wacana kolonial (colonial discourse). Wacana merupakan senjata ideologis kolonialisme. Strategi penaklukan oleh kolonialisme bukan semata kekerasan fisik.2 Akan tetapi, kolonialisme juga menyertakan peranan berbagai institusi, para ilmuan,
1 Bedjo Riyanto, Mempermainkan Realitas dalam Realitas Main-main: Wong Cilik dalam Ruang Imajiner Iklan, dalam Budi Susanto SJ (ed.), Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 50-51. Menurut Riyanto, gambaran tersebut membongkar dominasi kaum bangsawan dan elit kolonial yang selama ini menjadi pusat, sekaligus alat untuk mempermainkan dan mengejek kaum pribumi. 2 Kekerasan dan pembantaian terhadap masyarakat pribumi mewarnai zaman merkantilisme antara tahun 1498-1763, sebagai awal penaklukan dan penghisapan sumber daya lokal oleh kapitalisme. Untuk lebih jelasnya lihat,
Wacana Kolonial dan Kritik Poskolonialisme | 2
penulis, peneliti, serta para ahli dari berbagai bidang. Ilmu pengetahuan berperan sebagai alat ideologis kolonialisme untuk membentuk kesadaran tertentu di kalangan masyarakat pribumi. Wacana kolonial menjadi isu utama dalam pemikiran Orientalisme Edward Said yang termaktub dalam Orientalism (1978). Said mengadopsi dan mengembangkan gagasan tersebut dari Foucault hingga menjadi satu jenis studi baru tentang kolonialisme. Said menggambarkan bahwa naskah-naskah literer, penelitian, dan berbagai tulisan Barat tentang Timur membantu menciptakan dikotomi antara Barat dengan pihak-pihak lain. Melalui gagasannya, Said ingin memperlihatkan bahwa pengetahuan orang-orang Eropa tentang non-Eropa adalah bagian dari proses mempertahankan hegemoni Eropa atas pihak-pihak lain. Barat mendemistifikasi status pengetahuan dan mengaburkan batas-batas antara ideologis dan obyektif.3 Pemikiran Said tentang analisa wacana kolonial dapat memberikan gambaran bahwa kolonialisme merupakan produksi ideologis lintas geografis, bidang, dan lintas teks.4 Pada wilayah praktis, penciptaan wacana kolonial sama sekali meniadakan subyek terjajah. Wacana kolonial menarasikan masyarakat pribumi, seolah menulis di atas kertas kosong tentang masyarakat yang sama sekali belum ditandai. Kolonial memberi nama, mencirikan, dan mengkaji masyarakat terjajah dalam kerangka kerja dan aturan-aturan yang telah mereka tentukan. Mereka memiliki otoritas penuh untuk menciptakan gambaran masyarakat pribumi. Kolonialisme mengonstruksi masyarakat pribumi menurut kehendak dan tujuan-tujuan kekuasaannya. Kolonialisme mengonstruksi masyarakat terjajah lewat dua cara yang saling menguatkan. Pertama, kolonialisme melakukan identifikasi masyarakat kolonial melalui wacana dengan kaidah-kaidah dan sistem pengetahuan. Kedua, menggabungkan bangunan struktur masyarakat yang mereka ciptakan dengan tatanan masyarakat terjajah melalui misi pemberadaban (civilizing mission). Pribumi malas merupakan contoh stereotip wacana kolonial yang nantinya akan diikuti oleh serangkaian diskursus moral pemberadaban masyarakat terjajah.5 Ungkapan Niuwenhuis merupakan contoh lain mengenai stereotip masyarakat pribumi. Frances Gouda mengutip esai Niuwenhuis dalam Indische Courant dan majalah Politiek Economische Bond yang mengatakan, siapa saja yang pernah membaca The Waning of the Middle Ages karya Johan Huizinga, pasti akan menemukan banyak kesamaan antara pandangan mistik orang Eropa di akhir Abad Pertengahan dengan mentalitas orang Jawa pada tahun 1920-an. Menurut
Jacques B. Gelinas, Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization, terj. Raimond Robitaille (London: Zed Books, 2003), hlm. 4-6. 3 Ania Loomba, Kolonialisme/Pascakolonialisme, terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Bentang, 2003), hlm. 59. 4 Robert J.C. Young, Postcolonialism: an Historical Introduction (United Kingdom: Blackwell Publishing, 2001), hlm. 385. 5 Lihat Simon Philpott, Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme, terj. Zuly Qodir dan Uzair Fauzan (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 48.
Wacana Kolonial dan Kritik Poskolonialisme | 3
Niuwenhuis, Timur adalah gambaran masyarakat feodal Eropa pada Abad Pertengahan. Persinggungan Barat modern dengan yang disebut budaya primitif dalam latar kolonial memunculkan wacana tentang dominasi dan pengendalian. Ini menjadi hasrat kolonial Eropa untuk menyusun sejumlah retorika upaya pemberadaban berdasarkan kerangka kami dan mereka.6 Barat menyusun retorika tersebut dalam berbagai tulisan-tulisan tentang masyarakat pribumi. Ini merupakan tahapan awal sebelum mereka melakukan penguasaan secara fisik. Produksi pengetahuan mengenai pribumi sejatinya adalah penjelasan pandangan mereka terhadap kaum pribumi, bukan sesuatu yang nyata dan obyektif. Pengetahuan inilah yang dikonsumsi orang-orang Barat. Praktik kolonial Belanda juga tidak jauh dari praktik seperti ini. Kolonial Belanda menganggap masyarakat pribumi sebagai masyarakat belum sempurna evolusi biologisnya. Bahkan, perkembangan masyarakat pribumi terhenti pada tahap awal evolusi mereka, sehingga masyarakat ini terus menjadi bocah dengan nalar kekanak-kanakan. Kenyataannya, praktik-praktik kolonialisme melenceng jauh atau malah berbanding terbalik dari misi pemberadaban. Bukannya tampil sebagai pahlawan, kolonialisme justru muncul sebagai makhluk terluka [dengan] pandangan kabur, yang hanya mampu melihat kepingan persepsi, demikian kata Gouda. Pemikiran kolonial tentang keunggulan peradaban Barat, kecanggihan teknologi Barat yang menjadi visi dunia, mewariskan keunggulan kulit putih atas kulit berwarna yang menciptakan hubungan yang timpang dengan pribumi.7 Praktik kolonialisme juga tidak serta-merta menghapus tatanan prakolonial. Tetapi memelihara tatanan, ideologi, struktur hierarkis dan unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Kolonialisme menggunakan kelicikan dan keliatannya dengan mencampuri fungsi lembaga pribumi dan membelokkannya agar sejalan dengan kepentingan kolonialisme. Intervensi tersebut disamarkan lewat penumpulan dan pembelokan fungsi lembaga dan struktur sosial masyarakat pribumi. Strategi ini menandakan budaya dominasi tanpa hegemoni. Kolonial menggabungkan tatanan masyarakat prakolonial dengan struktur sosial baru ciptaan mereka lalu menyebutnya sebagai tradisi. Mereka kemudian memelihara dan menerapkan tradisi tersebut melalui pembenaran ideologis.8 Penjajahan Belanda di Indonesia juga melakukan praktik yang tidak jauh berbeda. Kolonial Belanda berlindung di belakang, bahkan memanfaatkan, bangsawan kerajaan demi mencapai kepentingan kekuasaannya. Pada tahun 1900-an misalnya, Belanda memaksa seluruh kerajaan di Nusantara untuk mengakui kedaulatan kolonial melalui Deklarasi Singkat. Belanda menggunakan aura autokrasi tradisional Indonesia untuk menundukkan masyarakat
Lihat Frances Gouda, Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942, terj. Jugiarie Soegiarto dan Suma Riella Rusdiarti (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 208. 7 Ibid., hlm. 48-50. 8 Ibid., hlm. 47.
Wacana Kolonial dan Kritik Poskolonialisme | 4
pribumi dan memperoleh konsesi serta tanah yang mereka inginkan dari penguasa setempat.9 Hal tersebut menunjukkan, kolonial Belanda yang datang dari Eropa modern tidak bermaksud menghapus sistem feodal. Sebaliknya, sebagaimana kata Tjipto Mangoenkoesoemo, penguasa kolonial secara sintesis mendorongnya dan menstabilkannya!10 Praktik-praktik inilah yang menjadi kegelisahan Loomba tentang proses terciptanya masyarakat poskolonial. Dalam pandangan Loomba, kondisi masyarakat poskolonial tercipta sebagai hasil interaksi antara kolonialisme dengan tatanan masyarakat prakolonial. Sehingga, kritik poskolonial tidak sekadar menyalahkan kolonialisme sumber tunggal terciptanya kondisi poskolonial. Gerakan anti kolonialisme- imperialisme tidak bisa dilakukan dengan serta-merta menginginkan kembalinya masa lalu prakolonial. Sebab, kondisi masa lalu prakolonial telah (di)kabur(kan) oleh kolonialisme itu sendiri. Spivak juga berpendapat serupa. Menurutnya, masa lalu prakolonial justru telah hilang. Tidak ada kemurnian lagi di sana. Sejarah kolonialisme telah mempengaruhi kondisi prakolonial, dan kondisi prakolonial sulit dipisahkan dari jejak kolonialisme.11 Wacana kolonial mengandalkan perbedaan ras, etnis, dan budaya sebagai bagian dari aparatus kekuasaannya. Akan tetapi, proses interaksi antara kolonial dengan masyarakat pribumi jauh melenceng dari tujuan wacana kolonial. Di lain pihak, strategi peniruan masyarakat pribumi juga berbahaya bagi kekuasaan kolonial. Peniruan itu mengaburkan batas-batas antara penjajah dan terjajah. Proses meniru menjadi strategi masyarakat poskolonial untuk melakukan perlawanan atas kolonialisme. Strategi Perlawanan Poskolonial Masyarakat poskolonial melakukan perlawanan terhadap kolonialisme melalui pertukaran budaya penjajah-terjajah. Meskipun kolonial bersikukuh mempertahankan keunggulan budaya dan ras mereka lewat wacana kolonial, masih terdapat celah bagi masyarakat terjajah untuk melakukan kontra-hegemoni. Ada dua strategi yang dapat dilakukan untuk melawan hegemoni kolonial. Dua strategi tersebut bersumber dari pemikiran Derrida dan pemikiran Homi K. Bhabha. Berikut ini strategi perlawanan masyarakat poskolonial atas kolonialisme: 1. Dekonstruksi Wacana kolonial yang melakukan pelainan (othering) terhadap masyarakat terjajah lewat Orientalisme, telah menyebabkan pertentangan Timur dan Barat. Oposisi biner
9 W. F. Wertheim, Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Kajian Perubahan Sosial, terj. Misbah Zulfa Ellizabet (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 49. 10 Ungkapan ini disampaikan Mangoenkoesoemo dalam pidato pembukaan kongres Javanese Culture Development di Solo awal Juli 1918. Dikutip dari Gouda, Dutch Culture..., hlm. 208. 11 Ania Loomba, Kolonialisme..., hlm. 22-23.
Wacana Kolonial dan Kritik Poskolonialisme | 5
tersebut beroperasi melalui struktur bahasa dalam teks-teks kolonial. Ungkapan Derrida tidak ada sesuatu di luar teks12 menyiratkan bahwa preposisi tentang masyarakat terjajah berada dalam teks tersebut. Oleh karenanya, logika wacana kolonial tidak bisa lepas dari logika bahasa yang digunakan. Melakukan kontra-hegemoni terhadap wacana kolonial berarti mempertanyakan ulang teks-teks produk kolonialisme. Di sinilah peran dekonstruksi. Pemikiran dekonstruksi Derrida membongkar seluruh asumsi dan persepsi kolonial tentang masyarakat pribumi. Selain itu, dekonstruksi menjadi strategi politik perjuangan kelompok terabaikan, terdominasi, dan kelompok subaltern. Dekonstruksi memberikan suara terhadap mereka yang telah dilainkan (othered) oleh wacana kolonial. Kemudian mendorong mereka untuk membentuk sejarah dan identitasnya sendiri.13 Pengertian dekonstruksi di sini bukan memutarbalikkan oposisi biner sekadar untuk menjadi unggul. Dekonstruksi merupakan upaya untuk mencari kesejajaran yang disertai interval antara sebelum muncul sebuah konsep baru.14 Dominasi Barat tidak bisa lepas dari logosentrisme, di mana pengarang hadir sebagai subyek yang mempunyai otoritas terhadap makna teks.15 Otoritas tersebut digunakan untuk menggambarkan masyarakat sesuai dengan kehendak pengarang. Sebelum Derrida sebenarnya Heidegger sudah mengkritik kecenderungan logosentrisme Barat yang disebut destruksi. Namun hal itu belum sepenuhnya berhasil. Kemudian Derrida melanjutkan konsep destruksi dengan istilah baru yang lebih radikal, yakni dekonstruksi.16 Jika teks-teks Orientalisme menjadi senjata bagi Timur untuk berbeda secara epistemologis, dekonstruksi menjadi upaya membongkar seluruh bangunan pengetahuan Barat dan memaksa keluar darinya untuk memutuskan hubungan secara total. Pemutusan hubungan dengan bangunan pengetahuan Barat mengenai Timur dilakukan dengan bertolak dari teks-teks pengetahuan Barat. Karena dalam pandangan Derrida, konsep pengetahuan itu tidak lahir dengan sendirinya. Pengetahuan membutuhkan alat penyampai yaitu bahasa. Narasi muncul dari teks dan langsung berurusan dengan bahasa. Dalam hal ini, upaya dekonstruksi adalah mencermati bagaimana teks tersebut menuturkan wacana dan menciptakan klaim-klaim kebenarannya berdasarkan struktur bahasa. Dalam wacana kolonial, pembentukan makna dalam tulisan berlindung di balik
12 Kata aslinya, il ny pas de hors-texte, dikutip dari Muhammad Al-Fayyadl, Derrida (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. xii. 13 Haryatmoko, Derrida yang Membuat Resah: Rezim Dogmatis dan Kepastian, dalam Basis, Nomor 11-12, Tahun ke-56, November-Desember 2007, hlm. 5. 14 Stephen Morton, Gayatri Spivak: Ethics, Subalternity and the Critique of Postcolonial Reason (Cambridge: Polity Press, 2007), hlm. 46-47. 15 Muhammad Al-Fayyadl, Derrida, hlm. 16. 16 Ibid., hlm. 20-21.
Wacana Kolonial dan Kritik Poskolonialisme | 6
sistem-sistem pertentangan yang cenderung didiamkan atau sengaja dibangun oleh sang pengarang.17 Membongkar seluruh sistem pertentangan yang membentuk identitas penjajah dan terjajah, berarti memandang teks dan muatannya sebagai sesuatu yang tidak tetap dan berubah-ubah. Begitu pula, identitas masyarakat dalam stereotip kolonial bukan sesuatu yang tetap dan telah jadi. Oleh karena itu, identitas adalah sesuatu yang terusmenerus dimaknai, ditafsirkan, dan dibaca laiknya teks yang tak pernah selesai ditulis. Setelah meruntuhkan narasi dalam wacana kolonial, kebutuhan selanjutnya adalah membuka ruang kepada the Other, yang telah disingkirkan dari sejarah, untuk terlibat langsung dalam memaknai dunia. Runtuhnya pusat kebenaran mengandaikan masyarakat terjajah mampu merumuskan kembali identitas mereka melalui basis kesadaran mereka.18 Setelah bangunan pengetahuan dalam wacana kolonial runtuh, kebutuhan selanjutnya adalah menulis kembali teks-teks kolonial dengan menelanjangi wacana yang sebelumnya digunakan sebagai upaya penaklukan. Sebagai contoh, sebagaimana telah dibahas Alan Gardiner dan Hellen Tiffin, para penulis Karibia dan Afrika Selatan menulis kembali dan menyebarluaskan dan kolonisasi.19 Praktik diskursif yang telah mengasingkan masyarakat kolonial melalui wacana kolonial dibongkar dengan menulis ulang sejarah sosial masyarakat. Di sinilah pentingnya menulis (kembali) masyarakatnya dengan pandangan yang sama sekali berbeda dengan pandangan Orientalisme. Kebutuhan masyarakat poskolonial adalah menulis ulang asumsi wacana kolonial dan membongkar kekeliruan yang dilakukan Barat. Pembacaan dan penulisan kembali wacana kolonial berhubungan dengan pandangan Derrida tentang dekonstruksi mimesis. Dekonstruksi mimetik adalah meniru dalam rangka mencari kesejajaran dengan yang ditiru. Jadi bukan menghadirkan sepenuhnya apa yang ditirunya. Peniruan dekonstruktif, adalah untuk membongkar kebenaran tunggal yang hendak dipaksakan terhadap kelompok lain.20 Dekonstruksi mimesis masyarakat terjajah terhadap penjajah akan menggoyahkan kekuasaan wacana kolonial yang membagi dua identitaspenjajah dan terjajahsebagai sesuatu yang pasti (fixed). beberapa pandangan novel karya Defoe dengan menelanjangi penggunaan kata-kata dan kiasan oleh pengarang novel tersebut dalam melakukan invasi
Ibid., 21-23. Ibid., hlm. 212-213. 19 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, dan Helen Tiffin, Menelanjangi Kuasa Bahasa: Teori dan Praktik Sastra Poskolonial, terj. Fati Soewandi dan Agus Mokamat (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003), hlm. 299. 20 Muhammad Al-Fayyadl, Derrida, hlm. 96-97.
18
17
Wacana Kolonial dan Kritik Poskolonialisme | 7
2. Identitas Ruang Ketiga Dalam konteks lain, dekonstruksi peniruan atau mimesis yang digagas Derrida dapat berjalan seiring dengan gagasan Homi K. Bhabha mengenai ruang ketiga (third space) atau ruang antara (in-between).21 Jika dekonstruksi mimetik Derrida digunakan dalam fenomena bahasa, gagasan Homi K. Bhabha merupakan strategi mencari ruang persinggungan berbagai budaya dalam poskolonial. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, praktik kolonial mengelaborasi dan melanggengkan tata masyarakat pada masa prakolonial. Proses tersebut merupakan ruang interaksi antara budaya terjajah dan penjajah. Meskipun penjajah menjaga keasliannya untuk berbeda dengan pribumi, tegangan identitas antara penjajah dan terjajah tetap tak terhindarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa wacana kolonial yang tidak memberi kesempatan bersuara kepada subyek koloni dalam proses konstruksi identitas tidak berhasil sepenuhnya. Masyarakat kolonial masih tetap eksis dan mampu menembus batas oposisi biner yang diciptakan wacana kolonial, lalu membentuk ruang sendiri. Gambaran penting dalam wacana kolonial adalah, ia tergantung pada konsep kebekuan (fixity) konstruksi ideologis pelainan (othering). Kebekuan (fixity) yang dimaksud adalah paradoks mode representasi dalam tanda-tanda kultural, historis, dan rasial dalam wacana kolonial. Kegagalan wacana kolonial tersebut disebabkan oleh banyaknya perbedaan rasial dan kultural antara penjajah-terjajah. Sehingga oposisi biner dan esensialisme identitas tidak terealisasi. Sebaliknya, pertemuan budaya kolonial dan budaya masyarakat pribumi menghasilkan hibriditas dan ambivalensi dalam wacana poskolonial. Keragaman kultural adalah obyek yang epistemologis, di mana perbedaan kultural adalah proses dialog (enunciation) kebudayaan melalui proses konstruksi yang berasal dari sistem-sistem identifikasi kultural. Jika keragaman kultural menunjuk pada kategori perbandingan etik, estetik, maupun etnologi, perbedaan kultural merupakan proses melalui statemen pembedaan dari atau di dalam kebudayaan.22 Wacana kolonial oleh Bhabha dijembatani oleh liminalitas sebagai ruang antara (inbetween) berbagai penandaan identitas, yang menjadi proses simbolis interaksi antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, yang hitam dan yang putih.23 Liminalitas dapat menghidupkan ruang antara dari persinggungan budaya penjajah dan terjajah. Tampaknya Bhabha ingin mencari ketegangan terus-menerus di antara keduanya yang melahirkan hibriditas, dengan menyandingkan perbedaan identifikasi kultural antara terjajah dan penjajah. Produksi makna antar budaya mengisyaratkan bahwa wacana digerakkan oleh ruang antara yang disebut ruang ketiga ini, yang menggambarkan
Pembahasan yang lebih mendalam tentang pemikiran Bhabha, lihat Homi K. Bhabha, The Location of Culture (London and New York: Routledge, 2002). 22 Homi K. Bhabha, The Location, hlm. 34. 23 Ibid., hlm. 4.
21
Wacana Kolonial dan Kritik Poskolonialisme | 8
kondisi umum bahasa serta implikasi khusus wacana ke dalam sebuah strategi yang institusional dan performatif.24 Bhabha sendiri, sebagaimana disinggung di atas, menggunakan hibriditas dalam pengertian ruang antara (in-between) yang mengacu pada ruang ketiga (third space) dan pada ambivalensi terutama dalam konteks hubungan budaya kolonial.25 Sebenarnya, pengertian hibriditas versi kolonial adalah untuk mencangkokkan identitas tertentu berdasarkan kemurnian kultural dalam rangka memantapkan status kekuasaan kolonial. Kolonial mengajari masyarakat pribumi untuk meniru melalui kelompok perantara. Kelompok perantara tersebut adalah mereka yang mendapat pendidikan etis kolonial. Tujuan penciptaan kelompok perantara bagi kolonialisme adalah untuk mengukuhkan kekuasaan kolonial. Dalam pandangan kolonial, masyarakat perantara tersebut akan mengidentifikasikan dirinya dengan budaya penjajah, dan merasa menjadi wakil budaya Barat di hadapan masyarakat pribumi. Masyarakat terjajah dijadikan seolah-olah seperti penjajah, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Almost the same, but not quite dalam istilah Bhabha. Namun bagi penjajah, peniruan masyarakat terjajah akan terhambat oleh sifat kodrati yang membedakan Barat dan non-Barat.26 Pada praktiknya, individu kolonial sendiri tak jarang mengambil gagasan Barat untuk menentang pemerintah kolonial. Bahkan, apa yang kolonial hibridkan kepada masyarakat terjajah disejajarkan dengan gagasan kaum pribumi. Dengan hal ini, maka status kekuasaan kolonial menjadi terancam.27 Proyek pemberadaban kolonial yang hendak menuntun masyarakat terjajah, sekaligus memasukkan kelainan yang permanen, gagal menemukan wujudnya. Sebaliknya, kaum perantara hasil yang dibentuk politik etis misi pemberadaban (civilizing mission) tersebut menjadi senjata yang menghantam kekuasaan kolonial. Tulisan-tulisan Bhabha sendiri menegaskan, bahwa penjajah dan terjajah tidak independen satu sama lain. Justru keduanya bersifat relasional. Identitas-identitas kolonial itu, baik dari sisi penjajah maupun terjajah, tidak stabil, meragukan, dan selalu berubah. Hal tersebut mematahkan klaim kaum nasionalis maupun kolonialis tentang diri yang tunggal. Hal ini sekaligus memberi peringatan agar tidak menafsirkan perbedaan kultural dalam kerangka yang reduktif dan absolut.28 Ruang ketiga yang menjembatani wacana kolonial dan masyarakat terjajah yang digunakan untuk memulihkan identitas
24 Lihat J. Supriyono, Mencari Identitas Kultur Keindonesiaan, dalam Muji Sutrisno dan Hendar Putranto (ed.), Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas, cet. V (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 141.
25 John Hutnyk, Contact Zones: Hybridity and Diaspora, artikel, diunduh pada 29 Juni 2009 dari: http://translate.eipcp.net/strands/02/hutnyk-strands01. 26 Keith Foulcher, Mimikri Siti Nurbaya: Catatan untuk Faruk, Jurnal Kalam, Edisi 14, tahun 1999, hlm. 15. 27 Ania Loomba, Kolonialisme, hlm. 224-225. 28 Ibid., hlm. 230-231.
Wacana Kolonial dan Kritik Poskolonialisme | 9
pribumi adalah teks. Masyarakat terjajah menghadirkan realitas dirinya melalui berbagai media, misalnya film, novel, puisi, maupun tulisan lainnya. Hal tersebut menjadi ruang dekonstruksi wacana kolonial.29 Kebutuhan masyarakat poskolonial adalah memikirkan kembali pandangan mereka tentang identitas sosial dan budaya yang selama ini (di)kabur(kan) oleh kolonialisme. Dalam konteks poskolonial, hibriditas menjadi strategi untuk melakukan resistensi terhadap budaya dominan. Peniruan terhadap budaya dominan dalam konteks poskolonial menjadi siasat untuk merongrong kekuatan-kekuatan hegemonik dari pusat kebudayaan. Hibriditas menjadi tuntutan atas esensialisme identitas dan budaya. Pertemuan antara budaya metropolis dan budaya pinggiran menghasilkan sesuatu yang unik dan kreatif. Intensitas kontak berbagai budaya didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi. Hibriditas menabrak batas-batas wilayah kultural dan kenegaraan. Hal tersebut menuntut poskolonialisme untuk keluar dari batas-batas nasional. Hibriditas mengajak kita berpikir (kembali) bahwa bentuk-bentuk formasi identitas dan kebudayaan adalah sesuatu yang tidak tetap (fixed). Bhabha menawarkan hibriditas sebagai kamuflase yang mengacaukan, namun justru produktif. Hibriditas adalah cara baru memasuki dunia dan berhubungan dengan proses menafsirkan perbedaan budaya. Hibriditas tidak mengacu pada apakah budaya koheren atau tidak. Hibriditas lebih mengandung pengertian proses kultural daripada deskripsi kebudayaan. Hibriditas menjadi kunci bagi kritik kebudayaan serta kajian poskolonial.30 Dekolonisasi Pengetahuan Bentuk-bentuk representasi kolonial maupun neokolonial saat ini, dalam bentuk film, tulisan perjalanan, iklan, gambar, dan lain sebagainya, terhadap non-Barat selalu berhubungan dengan pertempuran imperial. Neokolonial kontemporer juga menghasilkan bentuk-bentuk tekanan representasi budaya yang timpang dalam berbagai kontes politik dan tatanan dunia modern. Munculnya representasi Dunia Ketiga merupakan proses konstruksi di mana Dunia Pertama terbentuk. Meskipun pengalaman representasi (antara penjajah dan terjajah) tidak sama antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Begitu pula, dampak yang muncul tergantung dari relasi kekuasaan yang ada.31 Kemunculan wacana kolonial maupun neokolonial menandakan, bahwa dunia Timur maupun Dunia Ketiga tak henti dipelajari dan direpresentasikan. Bagi negara-negara imperial, negara Dunia Ketiga bukan hanya kaya akan sumber daya, namun juga lahan bagi
J. Supriyono,Mencari Identitas, hlm. 142. John Hutnyk, Contact Zones: Hybridity and Diaspora, artikel, diunduh pada tanggal 29 Juni 2009 dari: http://translate.eipcp.net/strands/02/hutnyk-strands01. 31 Dibyesh Anand, Western Colonial Representations of the Other: The Case of Exotica Tibet, dalam New Political Science, Volume 29, Nomor 1, Maret 2007, hlm. 25.
30
29
Wacana Kolonial dan Kritik Poskolonialisme | 10
pengembangan ilmu pengetahuan mereka. Mereka melanjutkan penguasaan atas negara terjajah dalam berbagai proyek pengetahuan sebagai kelanjutan pemberadaban yang belum selesai di masa lalu kolonial. Pada dasarnya, sekian alasan tentang misi pemberadaban, menyembunyikan agenda penguasaan abadi di negara-negara berkembang. Tentu saja, pengetahuan yang mereka peroleh dari lumpur tanah jajahan di masa lalu, akan tetap mereka daku sebagai milik mereka. Menjajah, berarti mempelajari secara seksama detail masyarakat setempat. Mereka mempelajari, menuliskan kembali,
32
kemudian Melihat hal
memamerkan kepada publik dunia apa yang telah mereka temukan dan pelajari.
ini, Foucault sendiri mengatakan, efek dari kisah para pengembara telah memberikan sumbangan besar bagi pengetahuan Barat yang sebanding dengan pengumpulan data ilmiah secara sistematis.33 Tumpukan naskah yang dipelajari kolonialisme dari berbagai dunia di masa lalu, kelak mereka susun secara sistematis, kemudian dikembalikan ke negara Dunia Ketiga dalam berbagai bentuk teori lewat pendidikan. Negara-negara imperialis juga tidak segan memberikan fasilitas dan teknologi pada negara miskin dan berkembang untuk melanjutkan hegemoni kolonialisme masa lalu. Keberadaan fasilitas dan teknologi dalam pendidikan, pemberian beasiswa untuk mengakses pendidikan di negara metropolis Eropa, serta pengiriman pakar pendidikan ke negara berkembang lebih merefleksikan kebutuhan neokolonial daripada kesadaran masyarakat setempat. Hasil pendidikan tersebut adalah munculnya kelompok-kelompok elit masyarakat yang berorientasi pada Barat.34 Dalam konteks lain, pendidikan muncul sebagai bentuk hegemoni yang paling efektif saat ini. Hal ini tidak mengejutkan, hubungan antara negara industri lanjut atau kapitalisme tahap akhir mensyaratkan kolonisasi dalam bentuk-bentuk baru. Kolonisasi tersebut dilakukan melalui basis ekonomi, politik, dan kehidupan sosial di berbagai negara berkembang. Kolonialisme di masa lalu mencari bentuk baru hubungan hegemoni-dominasi dalam rangka mengukuhkan kekuasaannya atas dunia. Pendidikan menjadi jalan di mana negara imperialis memasukkan pengetahuan mereka. Akibatnya, negara-negara imperialis Dunia Pertama memegang kendali kebijakan, solusi atas permasalahan sosial, maupun ketergantungan ekonomi dan politik Dunia Ketiga. Globalisasi pengetahuan Barat terus-menerus mengukuhkan Barat sebagai yang legitimate, yang menentukan bentuk-bentuk pengetahuan, dan menentukan sumber-sumber pengetahuan. Ini menjadi modal hegemoni Barat terhadap negara di luar Barat. Pendidikan menjadi mungkin sebagai alat hegemoni ketika perkembangan zaman dan persoalan yang
32 Lihat penjelasan Gouda, terutama Bab VI, Anjungan Hindia Belanda Terbakar: Kehadiran Belanda di Pameran Kolonial se-Dunia di Paris, 1931, Frances Gouda, Dutch..., hlm. 344-407. 33 Linda Tuhiwai Smith, Dekolonisasi Metodologi, terj. Nur Cholis (Yogyakarta: Insist Press, 2005), hlm. xviii. 34 Philip G. Albatch, Education and Neocolonialism dalam Bill Ashcroft, Garreth Griffiths, and Helen Tiffin (Ed.), The Post-colonial Studies Reader (London and New York: Routledge, 1994), hlm. 452-456.
Wacana Kolonial dan Kritik Poskolonialisme | 11
dihadapi masyarakat membutuhkan hierarki pengetahuan dan teori yang berkembang pesat pula. Akan tetapi, produksi pengetahuan itu sendiri sudah dikendalikan, sehingga pendidikan dalam negeri hanya menjadi versi dari domestifikasi ilmu pengetahuan negara imperial. Domestifikasi pengetahuan dari pusat imperial ini menjadikan pengetahuan tidak kritis dan sering keluar dari konteks masyarakatnya. Alih-alih mengkritisi persoalan yang ada secara obyektif, pendidikan dan kelompok ilmuan menjadi komprador bagi imperialisme.35 Di sini kita akan sampai pada kesimpulan, bahwa kolonialisme-imperialisme, bukan hanya penghisapan secara ekonomi dan penundukan secara politik. Keduanya, kolonialismeimperialisme, merupakan praktik diskursif yang menyebar ke berbagai dimensi kehidupan. Ketergantungan negara bekas terjajah dengan penjajah dalam hal pengetahuan, adalah bukti praktik diskursif kolonialisme. Sehingga masyarakat terjajah kesulitan untuk melepaskan diri dari penjajahan. Masyarakat terjajah melakukan impor pengetahuan Barat sebagai prasyarat program berbagai bantuan yang dikucurkan imperial. Kita kembali pada Foucault dan Gramsci untuk realitas tersebut. Menurut Foucault, pengetahuan juga terdapat dalam peraturan-peraturan sebuah institusi serta keputusankeputusan politis. Pengetahuan itu sendiri adalah wilayah untuk melakukan koordinasi dan subordinasi atas berbagai pernyataan, sehingga sebuah konsep dapat diterima dan diaplikasikan.36 Fenomena di atas menunjukkan sebuah kecenderungan, di mana Barat hendak menundukkan negara-negara yang telah melakukan dekolonisasi formal untuk kembali dikuasai lewat pengetahuan. Selanjutnya, dengan menggunakan konsep hegemoni Gramsci sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kita bisa memahami hubungan dominatif antar negara. Dalam hal ini, negara metropolis imperial menggunakan ilmu pengetahuan untuk melakukan hegemoni. Maka benar kata Foucault, apa pun bentuknya, pengetahuan adalah kekuasaan. Kita pantas untuk curiga bahwa para intelektual hasil pendidikan Barat menjadi perantara semakin kuatnya hegemoni Barat terhadap Timur atau secara umum dunia nonBarat. Tentu saja peran mereka sebagai tangan panjang hegemoni teori dan pengetahuan Barat tidak bisa diabaikan begitu saja. Bagaimanapun, kaum intelektual adalah benteng masyarakat. Persoalannya bukan pada salah atau benar individu yang memperoleh pendidikan Barat. Karena beberapa tokoh yang lantang mengkritik imperialisme justru berada di pusat imperial. Persoalannya adalah bagaimana seorang intelektual memandang masyarakatnya. Apakah ia mewakili cara pandang (neo)kolonialis-imperialis atau apakah ia menjadi wakil masyarakatnya. Dan ini adalah sebuah pilihan.
Linda Tuhiwai Smith, Dekolonisasi, hlm. 86-88. Lihat Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, terj. A.M. Sheridan Smith (London: Tavistock, 1972), hlm. 182-184.
36
35
Wacana Kolonial dan Kritik Poskolonialisme | 12
Penutup Dekolonisasi formal sudah dicapai oleh negara-negara terjajah. Indonesia pun sudah memproklamirkan kemerdekaan sebagai negara-bangsa lebih dari setengah abad silam. Namun, apakah dekolonisasi adalah pencapaian kemerdekaan sejati? Penting untuk merenungkan pertanyaan ini. Sebab, berbagai persoalan yang muncul sebagai residu kolonialisme-imperialisme masih berlangsung hingga kini. Dampak kolonialisme bukan hanya dampak ekonomis-politis. Kolonialisme juga membentuk mental dan karakter bangsa kita melalui wacana yang mereka tebarkan di masa lalu kolonial. Bayang-bayang masa lalu tersebut masih terasa hingga kini, bahwa kita adalah bangsa yang lemah, yang selalu butuh bantuan, yang tertinggal, dan lain sebagainya. Memang, kolonialisme adalah sejarah kelam perjalanan bangsa kita. Namun, hal itu juga bukan satu-satunya pembentuk mental dan karakter umum masyarakat kita. Feodalisme yang berlangsung selama berabad-abad, yang bahkan dipelihara oleh penjajah, juga menjadi pembentuk karakter masyarakat. Persoalan mentalitas dan karakter masyarakat mestinya juga menjadi prioritas dalam pembangunan. Jika wacana kolonial dapat kita simpulkan sebagai pembentuk kesadaran pribumi, maka menata kembali kesadaran sebagai bangsa yang merdeka adalah menata pengetahuan. Hal ini berarti mengembangkan pengetahuan, membangun kesadaran intelektual, dan kesadaran untuk memandang diri sendiri sebagai masyarakat yang merdeka. Peran intelektual dalam poskolonial adalah wakil mereka yang terpinggirkan dan kelompok-kelompok subaltern.
Wacana Kolonial dan Kritik Poskolonialisme | 13
Daftar Pustaka
Al-Fayyadl, Muhammad. Derrida. Yogyakarta: LKiS, 2005. Anand, Dibyesh. Western Colonial Representations of the Other: The Case of Exotica Tibet, New Political Science, Volume 29, Nomor 1, Maret 2007. Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, dan Helen Tiffin, Menelanjangi Kuasa Bahasa: Teori dan Praktik Sastra Poskolonial, terj. Fati Soewandi dan Agus Mokamat. Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003. Ashcroft, Bill, Garreth Griffiths, dan Helen Tiffin (Ed.), The Post-colonial Studies Reader. London and New York: Routledge, 1994. Bhabha, Homi K. The Location of Culture. Routledge: London and New York, 2002. Foucault, Michel. The Archaeology of Knowledge, terj. A.M. Sheridan Smith. London: Tavistock, 1972. Foulcher, Keith. Mimikri Siti Nurbaya: Catatan untuk Faruk, Jurnal Kalam, Edisi 14, tahun 1999. Gelinas, Jacques B. Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization, terj. Raimond Robitaille. London: Zed Books, 2003. Gouda, Frances. Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942, terj. Jugiarie Soegiarto dan Suma Riella Rusdiarti. Jakarta: Serambi, 2007. Haryatmoko, Derrida yang Membuat Resah Rezim Dogmatis dan Kepastian, Basis, Nomor 1112, Tahun ke-56, November-Desember 2007. Hutnyk, John. Contact Zones: Hybridity and Diaspora. Artikel, diunduh pada 29 Juni 2009, dari: http://www.translate.eipcp.net/strands/02/hutnyk-strands01. Loomba, Ania. Kolonialisme/Pascakolonialisme, terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Bentang, 2003. Morton, Stephen. Gayatri Spivak: Ethics, Subalternity and the Critique of Postcolonial Reason. Cambridge: Polity Press, 2007.
Wacana Kolonial dan Kritik Poskolonialisme | 14
Riyanto, Bedjo. Mempermainkan Realitas dalam Realitas Main-main: Wong Cilik dalam Ruang Imajiner Iklan, dalam Budi Susanto SJ (ed.), Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia. Yogyakarta: Kanisius, 2003. Simon Philpott, Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme, terj. Zuly Qodir dan Uzair Fauzan (Yogyakarta: LKiS, 2003). Smith, Linda Tuhiwai. Dekolonisasi Metodologi, terj. Nur Cholis. Yogyakarta: Insist Press, 2005. Sutrisno, Muji dan Hendar Putranto (Ed.). Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas. Yogyakarta: Kanisius, 2004. Wertheim, W.F. Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Kajian Perubahan Sosial, terj. Misbah Zulfa Ellizabet. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999. Young, Robert J.C. Postcolonialism: an Historical Introduction. United Kingdom: Blackwell Publishing, 2001.
Mujibur Rohman alumni Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Artikel pernah dimuat di Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 4, N0. 2, April 2010, hlm. 161177. Versi web dipublikasikan pada Desember 2010.
Mujibur Rohman
Untuk mengutip versi ini: Mujibur Rohman, Wacana Kolonial dan Kritik Poskolonialisme. Artikel, [tanggal akses] dari: . [halaman website]
You might also like
- Teori PascakolonialismeDocument25 pagesTeori PascakolonialismePrincessFyfie100% (37)
- Sejarah GroupDocument29 pagesSejarah GrouppinkNo ratings yet
- 5267 13447 1 SMDocument19 pages5267 13447 1 SMSalma DhiyaNo ratings yet
- Postkolonialisme: Definisi, Sejarah, Dan Kajian SastraDocument10 pagesPostkolonialisme: Definisi, Sejarah, Dan Kajian SastraJanoval RizkiNo ratings yet
- Makalah DR - YahyaDocument10 pagesMakalah DR - YahyaIlham Al-mandaryNo ratings yet
- Dekonstruksi Identitas (Neo) Kolonial: Sebuah Agenda Teologi PostkolonialDocument24 pagesDekonstruksi Identitas (Neo) Kolonial: Sebuah Agenda Teologi PostkolonialAlfirson BakarbessyNo ratings yet
- Penerapan Kerja Rodi Pada Masa Penjajah Belanda Terhadap Manusia PribumiDocument15 pagesPenerapan Kerja Rodi Pada Masa Penjajah Belanda Terhadap Manusia PribumiDwi NisfiNo ratings yet
- Manusia IndonesiaDocument22 pagesManusia IndonesiaFerdian HarahapNo ratings yet
- 4 Bab1 PDFDocument18 pages4 Bab1 PDFAzizah AzzahraNo ratings yet
- Filsafat PostkolonialismeDocument8 pagesFilsafat PostkolonialismeBaiqDwiIntanNo ratings yet
- TEORI POSKOLONIALDocument23 pagesTEORI POSKOLONIALFauziah sri karmala0% (1)
- Problem - Kewarganegaraan - Indonesia - Kontemporer With Cover Page v2Document23 pagesProblem - Kewarganegaraan - Indonesia - Kontemporer With Cover Page v2Rangga BachtiarNo ratings yet
- Pengantar Historiografi Modern Indonesia PDFDocument36 pagesPengantar Historiografi Modern Indonesia PDFEni KiryaniNo ratings yet
- Mitos Peribumi MalasDocument27 pagesMitos Peribumi MalasMustaza KukuyayaNo ratings yet
- Makalah Analisis LarasatiDocument13 pagesMakalah Analisis Larasatinovialita nabilah100% (1)
- Teori Postkolonial Dalam Kerangka KonsepDocument15 pagesTeori Postkolonial Dalam Kerangka KonsepTaufikOemamNo ratings yet
- POS-KOLONIALISMEDocument7 pagesPOS-KOLONIALISMEFerry HidayatNo ratings yet
- Peran Dan Partisipasi Pemuda Dalam Membangun Karakter BangsaDocument7 pagesPeran Dan Partisipasi Pemuda Dalam Membangun Karakter BangsaJames FaotNo ratings yet
- A Comparison On Indonesian and South Kor f02c8166Document11 pagesA Comparison On Indonesian and South Kor f02c8166Naila IzzatiNo ratings yet
- Teori Postkolonial Dalam Konteks IdentitDocument18 pagesTeori Postkolonial Dalam Konteks IdentitJamaluddin MohammadNo ratings yet
- Teori SastraDocument13 pagesTeori SastraTristan RokhmawanNo ratings yet
- Ken Miryam - Masyarakat Adat Dan KeindonesiaanDocument12 pagesKen Miryam - Masyarakat Adat Dan KeindonesiaanKen Miryam VivekanandaNo ratings yet
- BAB VII Teori PoskolonialDocument16 pagesBAB VII Teori PoskolonialAf AysNo ratings yet
- Filsafat UASDocument12 pagesFilsafat UASDaffa RevanzaNo ratings yet
- Tokoh POSKOLONIALISDocument4 pagesTokoh POSKOLONIALISFathia Az-ZahraNo ratings yet
- 1 PBDocument10 pages1 PBNanditoNo ratings yet
- Tokoh Dan Teori AntropologiDocument21 pagesTokoh Dan Teori AntropologinakaNo ratings yet
- Respon Bangsa Indonesia Terhadap Kolonialisme Dan Imperialisme Di Bidang Seni SastraDocument5 pagesRespon Bangsa Indonesia Terhadap Kolonialisme Dan Imperialisme Di Bidang Seni SastraIkrimainur WahidahNo ratings yet
- TEORI POSTKOLONIAL DALAM SASTRADocument7 pagesTEORI POSTKOLONIAL DALAM SASTRARizki FahmiNo ratings yet
- Tugas PKNDocument3 pagesTugas PKNzen ZehbiNo ratings yet
- 1 08 AmDocument10 pages1 08 AmArief RochmanNo ratings yet
- Makalah Kelompok 10 Historiografi IndonesiaDocument11 pagesMakalah Kelompok 10 Historiografi IndonesiaCek NayuNo ratings yet
- Perkembangan Antropologi IndonesiaDocument6 pagesPerkembangan Antropologi Indonesiaafif futaqi67% (6)
- Tugas Review Sos Budaya Ke-8, Cultural StudiesDocument5 pagesTugas Review Sos Budaya Ke-8, Cultural StudiesHandyyNo ratings yet
- Resensi Buku Karya JC Van LeurDocument9 pagesResensi Buku Karya JC Van LeurGanda Febri Kurniawan100% (3)
- Kajian TEORI PostkolonialDocument19 pagesKajian TEORI PostkolonialFadly MNo ratings yet
- Ulasan Ilmu KolonialDocument7 pagesUlasan Ilmu KolonialPuteri ShahliaNo ratings yet
- Post ColonialDocument3 pagesPost ColonialNORATIKAH BINTI ISMAILNo ratings yet
- Teori PoskolonialDocument1 pageTeori Poskolonialatikarohmawati0001No ratings yet
- babII 2Document15 pagesbabII 2Sarah Sakinah AhmadNo ratings yet
- Materi Kajian Prosa Fiksi IndonesiaDocument14 pagesMateri Kajian Prosa Fiksi IndonesiaAfifah nur FajriahNo ratings yet
- MULTIKULTURALISMEDocument4 pagesMULTIKULTURALISMEHeru ArdiansyahNo ratings yet
- Teori postkolonialisme dan definisinyaDocument2 pagesTeori postkolonialisme dan definisinyaFSD Univ. Potensi UtamaNo ratings yet
- Nota Kuliah GIG1012 DEKOLONISASI For StudentDocument22 pagesNota Kuliah GIG1012 DEKOLONISASI For StudentNUR AISYAH MOHD TAHIRNo ratings yet
- Konsep NasionalismeDocument4 pagesKonsep NasionalismeRiky SaputraNo ratings yet
- Dampak Kolonialisme Terhadap IndonesiaDocument8 pagesDampak Kolonialisme Terhadap IndonesiaSiprianus Adi Wardhana JabarmaseNo ratings yet
- ILUSI DEKOLONISASIDocument27 pagesILUSI DEKOLONISASIHizkia Yosie PolimpungNo ratings yet
- Iman, Sastrawan, Dan Karya SastraDocument10 pagesIman, Sastrawan, Dan Karya SastraM Irfan HidayatullahNo ratings yet
- POSTKOLONIALISMEDocument13 pagesPOSTKOLONIALISMEDino 6969100% (1)
- Akar-Akar Nasionalisme Dan Demokrasi Di IndonesiaDocument7 pagesAkar-Akar Nasionalisme Dan Demokrasi Di Indonesiaeta piana100% (1)
- Kutipan Tulisan, Pemikiran Soedjatmoko, Kritis, Mencerahkan.Document63 pagesKutipan Tulisan, Pemikiran Soedjatmoko, Kritis, Mencerahkan.Muh Nurfaiz FahmiNo ratings yet
- Essay: 1. Nyoman Kutha Ratna, "Poskolonialisme Indonesia: Relevansi Sastra" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 205Document7 pagesEssay: 1. Nyoman Kutha Ratna, "Poskolonialisme Indonesia: Relevansi Sastra" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 205DiasNo ratings yet
- Konsep Civilization Dibawa Oleh Orang EropaDocument5 pagesKonsep Civilization Dibawa Oleh Orang EropaJuca Ai YolandaNo ratings yet
- Tugas Teori PostkolonialDocument3 pagesTugas Teori PostkolonialRAISA DAYANANo ratings yet
- MakalahDocument5 pagesMakalahmuiixie6No ratings yet
- PancasilaDocument5 pagesPancasilasaila salsabilaNo ratings yet
- Makalah KIK HISKI XX 2009 - M Saleeh & Prof. Dr. M MokhtarDocument33 pagesMakalah KIK HISKI XX 2009 - M Saleeh & Prof. Dr. M MokhtarThasswhin ManimaranNo ratings yet
- Isi Laporan Asistensi KosmonasfunDocument62 pagesIsi Laporan Asistensi KosmonasfunRizka KhairaniNo ratings yet