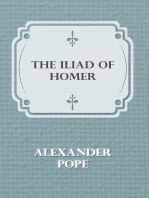Professional Documents
Culture Documents
Otonomi Desa
Uploaded by
Akuan Cecep RammdaniCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Otonomi Desa
Uploaded by
Akuan Cecep RammdaniCopyright:
Available Formats
Otonomi Desa :Antara Harapan dan Kenyataan
Mei1 Oleh : Moh. Rusli Jamik Dalam suatu kesempatan, salah satu Bapak Proklamator Indonesia Bung Hatta pernah mengatakan tentang bagaimana menunbuhkan demokratisasi di Indonersia. Beliau berpesan bahwa seharusnya kita bercermin atau belajar dari praktek-praktek demokrasi yang tumbuh di desa. Karena dari desalah timbul demokrasi yang murni. Dalam pengertian ini semangat kedermawanan, sensitivitas dan kepedulian saling membantu dan saling berembuk serta tumbuhnya prakarsa lokal merupakan modal sosial bagi tumbuhnya sikap hidup demokratis, khsususnya dalam soal kepemimpinan, misalnya dalam pemilihan kepala desa, yang sudah sejak lama tumbuh berakar di masyarakat desa. Tradisi ini secara tidak langsung memberikan cerminan yang cukup kuat tumbuhnya demokrasi di pedesaan. Selengkapnya klik disini Mengenang kembali apa yang diucapkan Bung Hatta, teringat beberapa waktu yang lalu di sebagian besar desa di kabupaten di Madura, dimana telah diadakan pesta demokrasi yaitu perhelatan pemilihan kepala desa. Dinamika masyarakat desa seakan hidup kembali penuh antusiasme dalam rangka menentukan pemimpin mereka. Namun patut juga diakui, meskipun disana sini realitanya terjadi kekurangan dalam pelaksanaannya tetapi pada dasarnya pesta tersebut merupakan cerminan pelaksanaan demokratisasi di masyarakat desa. Memang tidak bisa dipungkiri adanya kelemahan dalam pelaksanaanya, seperti praktek permainan uang (money politik), adanya hegemoni para broker atau petualang, perjudian yang bermain didalam kancah arena pemilihan kepala desa tersebut. Itulah warna dari sebuah pesta demokrasi. Dan kita harus dan wajib mendukung memelihara dan melaksanakan apa yang telah dilakukan masyarakat desa, berkenaan dengan pesta demokrasi tersebut, sambil lalu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi. Satu hal perlu mendapatkan perhatian bersama, bahwa praktek pemilihan pemimpin secara langsung merupakan modal dasar sebuah demokratisasi. Modal dasar dalam bentuk pemilihan kepala desa secara langsung inilah merupakan saham berharga dalam rangka menumbuhkan suasana demokratisasi di desa. Namun satu hal yang perlu kita perhatian bersama bahwa dalam rangka untuk mewujudkan desa yang mandiri, desa yang bisa melaksanakan semua kegiatan berdasar prakarsa lokal, sebagaimana disebutkan Bung Hatta, modal dasar demokrasi, yang berbentuk pemilihan kepala desa secara langsung bukan satu-satunya yang bisa membawa masyarakat desa menuju kesejahteraan bersama. Mengapa ? karena demokratisasi tanpa adanya otonomi yang luas bagi desa, maka demokrasi tersebut bagaikan orang berjalan dengan satu kaki. Mereka akan timpang didalam melaksakan apa yang diharapkan. Untuk itu, selain demokrasi, pemberian otonomi desa merupakan hal yang sangat mendasar, dan satu hal yang tidak bisa dipungkiri, pemberian otonomi bukan tuntutan sepihak sebab pemerintah pusat punya otonomi, propensi diberi otonomi, kabupaten juga demikian, kecamatan apa lagi. Persoalannya mengapa pemerintah desa tidak diberi kesempatan untuk juga melakukan sesuai dengan kemampuan, kapasitas, keinginan masyarakat tersebut. Ini sebenarnya tidak
bertentangan dengan aturan yang berlaku, semua hal, apalagi dalam dunia sekarang ini bahwa pemberiaan kewenangan yang luas kepada para aparatur pemerintah, tidak terkecuali di desa itu merupakan satu keniscayaan. Tetapi persoalannya, adakah otonomi di desa ? Inilah yang menjadi masalah urgen dalam rangka untuk mendorong terwujudnya otonomi di desa. Dengan demikian untuk menciptakan desa yang mandiri, kreatif berdasarkan prakarsa lokal tidak hanya cukup dengan tumbuhnya demokratusasi dalam bentuk kepemimpinan yang dipilih langsung, tetapi juga bagaimana memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengelola kegiatan-kegiatan pembangunan sebagaimana yang diinginkan masyarakat desa. Untuk itu, perlu mendapat perhatian bersama. Berbicara otonomi daerah, sebenarnya secara konsep pada dasarnya mengandung prinsip atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Artinya daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Dalam arti otonomi daerah bukan sekedar otonomi untuk pemerintah daerah, tetapi lebih dari itu, juga otonomi bagi masyarakat daerah. Jadi dengan demikian tujuan dari otonomi daerah untuk menjadikan penyelenggaran pemerintah lebih efisien dan transparan. Daerah memiliki keleluasaan menjalankan kewenangan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan daerah. Dalam menerjemahkan dan merealisasikan kondisi itu tentu saja pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri, ada kewajiban untuk melibatkan masyarakat. Karena masyarakat sebagai pihak yang nanti terkena dampak dari sebuah kebijakan. Oleh karena itu masyarakat selayaknya untuk ikut menentukan sesuai kebutuhannya. Inilah inti pokok kontrol masyarakat sebagai kunci dari transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya transparansi, penyimpangan dari sebuah implementasi kebijakan bisa ditekan dan dampaknya pada efisiensi dan efektifitas kebijakan itu sendiri. Otonomi daerah pada dasarnya membuka kunci yang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk menjadikan program pembanguan lebih realistis, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Artinya peluang untuk terjadinya ketidaktepatan, kesia-sian bahkan pemborosan bisa dikendalikan dengan sekecil-kecilnya. Berdasarkan konsep ideal otonomi daerah tersebut, timbul sebuah pertanyaan, lantas bagaimana dengan otonomi di desa ? Kalau kita membicarakan tentang desa, biasanya yang muncul selalu masalah dan masalah yang hampir tidak ada habis-habisnya. Meskipun desa dalam sejarah perkembangan bangsa ini merupakan wujud pemerintahan terbawah tapi pada kenyataan bahwa desa selalu ditempatkan pada posisi yang marginal. Mengapa ? karena desa yang dianggap organ negara yang paling bawah, secara tata kerja birokrasi pemerintahan selama ini dianggap sebagai kaki tangan pemerintah pusat secara khirarhis. Sebagai contoh pada zaman orde baru, desa dianggap sebagai suatu organ sosial politik yang sewaktu-waktu bisa dimobilisasi dukungan politik masyarakat untuk partai tertentu pada saat pemerintah berkuasa. Memang nasib sial selalu meninpa pada desa. Adanya reformasi sedikit melegakan bagi desa dengan ditetapkannya UU no. 22/1999 dan kemudian direvisi menjadi UU no. 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini memberi pengakuan bagi desa untuk melaksanakan prakarsanya berdasar hak asal usul daerahnya. Namun, sayangnya dalam pelaksanaan lebih lanjut tentang desa, pengaturannya masih diserahkan pada pengambil kebijakan ditingkat kabupaten/kota. Akibatnya, dinamika social politik di desa menjadi sangat tergantung kepada dinamika sosial politik yang terjadi di
kabupaten/kota. Misalnya, kerap terjadi nasib desa terkatung-katung karena tidak ada respon dari pemerintah kabupaten/kota. Sangat ironis memang, tetapi itu faktanya. Sebenarnya adanya reformasi dan otonomi daerah dapat memberi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya. Otonomi daerah, memberi peluang bagi aparat desa untuk membuka ruang dan mengembangkan kreatifitas dalam mengelola desa. Bagi masyarakat memberi kesempatan untuk menggali potensi lokal yang ada, sehingga bisa membawa kesejateraan. Inilah sebenarnya yang memberi harapan bagi pemerintah desa untuk lebih leluasa menentukan program pembangunan mana yang diperlukan sehingga sesuai dengan kemampuan masyarakat. Memang membicarakan desa kita harus realistis bahwa desa juga memiliki kelemahan dan persoalan yang serius didalamnya. Diantaranya pertama, adanya tokoh figur yang kuat, yang biasanya diwakili oleh kepala desa, seringkali menjadi hambatan dalam tumbuhnya demokrasi desa. Kuatnya sifat paternalistik pada masyarakat desa bahwa lurah dianggap sebagai seorang yang dituakan, sebagai bapak yang harus mengayomi dan melindungi. Inilah yang menjadi kendala dalam menumbuhkan relasi sosial politik di desa. Karena yang muncul dan berkembang biasanya adalah budaya sungkan. Nah budaya inilah akhirnya menjadi faktor penghambat relasi politik di desa yang terbangun dan diinginkan secara egaliter dan demokratis. Sehingga dengan demikian hal-hal tersebut akan menumbuhkan budaya pelaksanaan pemerintahan yang jelek (bad governance). Kedua, seperti yang banyak kita lihat bahwa acuan dari keberhasilan otonomi desa banyak hanya ditentukan dan dilihat semata dari ukuran ekonomi. Sedikit orang yang melihat bahwa otonomi desa itu pada dasarnya adalah apakah di desa tersebut sudah tumbuh dan berkenbang tentang bagimana pengelolaan pemerintahan, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, itu sebenarnya esensi dari otonomi desa. Jadi bukan semata-mata ukuran ekonomi. Ketiga, dari faktor ekstern muncul adanya anggapan bahwa masyarakat dan pemerintah desa, merupakan bawahan dari pemerintah kabupaten atau bupati. Desa dianggap sebagai perpanjangan tangan bupati. Pada hal sebenarnya desa adalah unit pemrintahan yang otonom. Oleh karena itu maka anggapan yang demikian harus diubah bahwa kedudukan desa dibawah bupati sejujurnya hanya tepat jika dikaitkan dengan urusan birokrasi semata. Di era otonomi seperti sekarang, cara pandang demikian kurang tepat, karena pemerintah desa memiliki hak yang sama dalam mengelola desanya sesuai dengan kewenangan yang diberikan terhadapnya. Namun apa yang terjadi, adanya semangat desentralisasi yang belum dipahami secara benar oleh aparat negara yang ada di daerah sehingga akibatnya desa masih tetap saja ditempatkan sebagai stuktur pemerintahan yang paling bawah. Selain itu ditambah oleh adanya prilaku aparat birokarsi kabupaten yang tidak mau membuka diri dan responsip terhadap tuntutan desa, karena menganggap di desa sumber daya manusianya masih lemah, tidak mampu mengelola dan melaksanakan pemerintahan sendiri, sehigga menganggap bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah contoh bukti kesalahan-kesalahan secara mendasar aparat pemerintah kabupaten dalam memahami perubahan paradigma otonomi. Meskipun demikian, kenyataaannya bahwa adanya kelemahan sumber daya manusia di desa justru tidak pernah direspon secara baik oleh kabupaten, paling tidak bagaimana memberikan pemberdayaan, fasilitas, supervisi dalam rangka untuk meningkatkan, merubah kemamapuan aparat desa. Kalaupun mungkin dilakukan hanya pada aspek yang bersifat formal saja yang pada dasarnya tidak menyemtuh akar persoalan di desa. Banyak contoh membuktikan bahwa adanya ketidakpedulian aparat kebupaten melihat relitas kelemahan di desa
Selain itu, dengan otonomi desa, masyarakat bisa merasakan adanya pengelolaan desa lebih transparan, prosedur birokrasi yang gampang, pelaksanaan demokrasi menjadi lebih semarak dan dinamis, yang secara langsung atau tidak akan membawa dampak partisiapsi optimal dari masyarakat. Sebagai misal, pada pemilihan kepala desa, bila dulu ada Litsus (penelitian khusus) untuk calon-calon kepala desa, maka sekarang sudah tiada. Pemilihan kepala desa benar-benar menjadi ajang pencarian pemimpin desa secara demokratis dan transparan. Disisi lain, dalam pertanggungan jawab kinerjanya, kepala desa tidak lagi kepada bupati tetapi pada warga masyarakat pemilih yang diwakilkan dalam wadah apa yang disebut Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai wujud wakil rakyat desa. Namun peluang ini bukan tanpa persoalan, banyak kendala masih menyelimuti pelaksanaan otonomi di desa, beberapa diantaranya, pertama, belum hilangnya paradigma bahwa pemerintah desa masih berposisi sebagai bawahan bupati dibanding sebagai pemerintahan otonom. Selama ini belum berubah atau keluar dari stereotepe yang demikian, sulit rasanya peluang desa untuk menjadi entitas social politik yang otonom. Karena itu perlu upaya untuk menghilangkan cara pandang pada semua aparat di kabupaten bahwa desa merupakan struktur pemerintahan terendah di bawah kabupaten. Pandangan ini mungkin hanya relevan jika berhubungan dengan urusan birokrasi. Situasi ini diperparah lagi dengan anggapan dari aparat kabupaten yang tidak mau membuka diri dan peka terhadap tuntutan desa. Alasan pembenar yang biasa dipakai adalah, karena desa masih dianggap lemah ditinjau dari sumber daya manusia, sehingga tidak layak untuk memberi otonomi di desa. Ini bukti akibat kurangnya pengertian dari aparat dalam memahami paradigma otonomi. Yang patut disayangkan lagi, meski sudah menganggap sumber daya manusia di desa masih lemah untuk diberi otonomi, namun tidak ada upaya dari kabupaten untuk melakukan fasilitasi dan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia di desa secara terprogram. Kalaupun ada, program yang dilakukan, biasanya hanya sekedar dalam rangka menggugurkan kewajiban prosedural saja, tanpa menyentuh aspek substansial yang berkembang di masyarakat. Sebagai misal, minimnya pemahaman para anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) terhadap tugas pokok dan fungsinya. Dampaknya terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi antara pemerintah desa dengan BPD yang biasanya dipicu oleh ketidaktahuan terhadap tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Seperti sikap BPD yang berposisi sebagai oposisi dibandingkan sebagai mitra kerja dari pemerintah desa. Desa masih dilihat dari persektif negara (kabupaten) bukan dari perspektif masyarakat desa sebagai soal kedua. Anggapan seperti ini tidak akan mendorong terbentuknya otonomi desa. Karena kabupaten masih menganggap dirinya lebih berhak mengatur desa serta memandang desa masih belum mampu untuk mengelola kehidupannya secara mandiri. Ini terlihat jelas dari banyak urusan yang sebenarnya merupakan intern desa, banyak diambil alih kabupaten, sehingga tidak ada ruang bagi desa untuk melakukan pengelolaan pemerintahan dalam konteks self governing community. Seperti penentuan model rekrutmen kepemimpinan desa, perkembangan demokrasi di desa, mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa serta pengaturan wilayah desa. Jadi semua produk kebijakan yang dibuat desa, baik oleh kepala desa maupun BPD harus selalu mengacu kepada kebijakan dari kabupaten. Ketiga, adanya gap atau tidak adanya integrasi antara keinginan desa dengan keinginan kabupaten dalam penyusunan anggaran. Desa dalam menyusun anggarannya masih harus mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh kabupaten. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) baru bisa dibuat oleh desa setelah adanya penetapan APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ditingkat kabupaten. Dampaknya apa? Timbulnya relasi anggaran yang tidak menguntungkan desa. Desa dibuat menunggu dan siap menerima berapapun alokasi anggaran yang ditetapkan kabupaten kepada desa tanpa adanya ruang bagi desa untuk ikut menentukan alokasi anggaran yang ideal bagi desa. Hasil penelitian IRE Yogyakarta, alokasi anggaran untuk desa masih belum proporsional. Paling banyak alokasi anggaran yang diberikan kepada desa, tidak sampai 4 % (persen) dari total DAU yang diterima oleh kabupaten. Padahal idealnya adalah 10% dari total DAU untuk tiap-tiap desa. Selain itu, dalam kaitan dengan keuangan, masalah pengaturan pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada di tingkat desa. Misalnya, pasar kabupaten yang ada ditingkat desa. Status pasar yang ada di desa, yang sebenarnya secara ekonomi bisa dipergunakan oleh desa untuk peningkatan pendapatan desa, kurang memberi kontribusi bagi desa, disebabkan karena dikelola kabupaten. Di satu sisi kabupaten masih menganggap pasar tersebut merupakan sumber untuk menunjang PAD (pendapatan asli daerah). Disisi lain desa mengangap pasar tersebut bisa menambah pendapatan desa untuk bisa mandiri. Sebenarnya, persoalannya bukan pada siapa yang paling berhak mengelola pasar desa tersebut, namun yang paling penting adalah bagaimana mengatur agar supaya pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada di desa bisa menjadikan desa mandiri. Jadi, jika kabupaten masih tetap mengelola pasar desa dan desa hanya mendapat bagi hasil dari pasar tersebut, tanpa adanya upaya pembelajaran dan tanpa memberi peluang mengelola bagi desa, maka harapan untuk menjadikan desa mandiri dan kuat secara ekonomi serta mampu menopang suksesnya otonomi daerah akan jauh panggang dari bara api untuk menjadi kenyataan. Keempat, Akibat adanya ketergantungan desa terhadap kabupaten dalam politik anggaran, maka proses pembangunan di desa juga mengalami ketergantungan. Upaya desa untuk menyediakan dan meratakan fasilitas publik maupun untuk menciptakan usaha ekonomi produktif desa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan mengalami hambatan karena minimnya dana. Yang penting lagi, rencana pembangunan desa yang dibuat melalui Musyawatrah Pembangunan Desa (Musbangdes) untuk diajukan ke tingkat kabupaten sering tak terealisir alias mubasir karena usulan tersebut tidak disetujui di tingkat Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) karena tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang dibuat kabupaten. Jadi tidak ada jaminan bagi desa, rencana pembangunan yang dibuat akan disetujuai oleh kabupaten, meskipun itu sudah melalui partisipasi masyarakat desa secara luas. Selain itu, untuk mendorong pembangunan di desa dengan cara memberi stimulan, pada tingkat tertentu justru malah membebani dan mengeksploitasi desa. Bagaimana tidak, kabupaten untuk menghilangkan tanggung jawab dalam pembangunan desa, modal yang sering dipakai adalah adanya semangat gotong royong yang dimiliki desa sebagai alasan pembenar. Artinya untuk melakukan pembuatan jalan, perbaikan atau pembuatan saluran irigasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan fasilitas publik, desa harus mencari dana sendiri secara mandiri untuk menambah dana stimulan tersebut yang diberikan kabupaten, yang jumlahnya jauh dari kebutuhan keseluruhan. Hal ini berbanding terbalik dengan upaya penyediaaan sarana di masyarakat kota. Hampir tidak pernah ada bahwa pembangunan kota dilakukan secara mandiri oleh masyarakat kota. Seperti; sarana jalan, penerangan, fasilitas publik, infrastruktur penunjang ekonomi kota pasti dibangun oleh pemerintah kabupaten. Inilah contoh bukti masih adanya bias pembangunan di era otonomi daerah.
Beri Kewenangan
Untuk membangun otonomi desa, idealnya desa diberikan kewenangan yang lebih luas dan jelas. Dan pada sisi lain kabupaten hendaknya mengurangi peran otoritasnya dalam mengurusi urusan desa yang sudah bisa dilakukan oleh desa. Kewenangan yang dibutuhkan desa diantaranya: pertama, kewenangan untuk ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintah kabupaten yang menyangkut tentang desa. Idealnya setiap kebijakan tentang desa, hendaknya melibatkan desa dalam setiap tahapnya. Misalnya, kebijakan tentang pemerintahan desa, kebijakan tentang penyusunan alokasi anggaran untuk desa dalam APBD, dan kebijakan program pembangunan kabupaten yang menyangkut tentang desa, harus melibatkan partisipasi desa. Artinya pelibatan partisipasi desa disini, tidak hanya aparat pemerintah desa tapi yang lebih penting adalah melibatkan semua elemen yang ada. Adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap keputusan merupakan cermin utama dari terciptanya demokratisasi dan desentralisasi desa. Kedua, memberi wewenang dalam urusan internal desa. Bagi desa-desa yang mampu mengurus urusan internalnya berilah keleluasaan untuk melakukannya. Misalnya pada penentuan model pemilihan kepemimpinan desa, pembentukan lembaga demokrasi desa, prosedur pertanggungjawaban pemerintah desa pada masyarakat, pengelolaan wilayah desa, pengelolaan pembangunan desa, dan anggaran desa. Pemberian kewenangan ini harus dibarengi dengan keleluasan bagi desa untuk menerjemahkan dan menafsirkan pedoman dan petunjuk dari kabupaten berdasar konteks lokalitas dan kesepakatan masyarakat. Ketiga, berilah wewenang untuk mengelola dana perimbangan yang berasal dari pembagian DAU. Pemberian tersebut tentu harus diikuti dengan syarat bahwa ada komitmen atau jaminan dari kabupaten untuk memberi prosentase yang wajar kepada desa atas DAU yang diterima kabupaten. Namun sebesar apapun fungsi dan kekuasaan yang dimilki desa, tanpa ditopang oleh fasilitas alat untuk menjalankan fungsi dan kekuasaan tidak akan mendorong terwujudnya otonomi desa. Karena tidak ada kemandirian dalam mengelola daerahnya. Keempat, memberi kewenangan dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada di desa. Artinya desa leluasa untuk mengelola, baik secara sendiri maupun dengan mengajak kerjasama dengan pihak luar untuk menggarap sumber daya alam yang tersedia di desa. Adanya sumber pendapatan daerah yang telah dikelola oleh kabupaten di tingkat desa, idealnya kabupaten memberi bagian yang proporsional pada desa, tentunya dengan pembagian yang harus dibicarakan bersama antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Dan andaikata, kabupaten merasa bahwa desa sudah cukup mampu mengelola secara mandiri, selayaknyalah kabupaten memfasilitasi untuk mengalihkan pengelolaan tersebut kepada desa. Kelima, adanya kewenangan untuk menolak segala bantuan dari pemerintah diatasnya yang tidak dikuti dengan pembiayaan yang sesuai, serta tidak sesuai dengan daya dukung masyarakat desa dan kehendak masyarakat setempat. Tetapi, lagi-lagi harus diikuti oleh adanya jaminan dari kabupaten bahwa penolakan tersebut bukan sebagai upaya pembangkangan, sehingga tidak timbul penilaian negatif dari kabupaten terhadap pemerintah desa. Sebagai kata akhir dari wacana singkat ini, bahwa pemberian kewenangan kepada desa tentunya tidak serta merta bisa diterapkan pada semua desa. Pemerintah kabupaten hendaknya juga melihat dan memilah, bagi desa yang sudah dianggap siap menerima pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab, bisa langsung menyerahkan sepenuhnya. Tetapi bagi desa yang dirasa belum mampu, maka kabupaten hendaknya memberikan fasilitasi untuk mendorong desa berupaya untuk siap. Andaikan proses seperti ini bisa berlangsung di setiap
kabupaten di Madura, maka impian untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan madani akan tercipta seperti harapan bersama. Semoga. Penulis: Direktur LP3M ParamadinaPrenduan-Sumenep dan Alumni S2 Sosiologi UNMUH Malang
You might also like
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionFrom EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2506)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5794)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersFrom EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersRating: 4 out of 5 stars4/5 (2306)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleFrom EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HoleRating: 4 out of 5 stars4/5 (4609)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20003)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (3270)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6510)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationFrom EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationRating: 4 out of 5 stars4/5 (2499)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)From EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (4345)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- Don Quixote: [Complete & Illustrated]From EverandDon Quixote: [Complete & Illustrated]Rating: 4 out of 5 stars4/5 (3845)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (2564)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2475)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19653)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)From EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (7769)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksFrom EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksRating: 4 out of 5 stars4/5 (7086)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionFrom EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (12943)













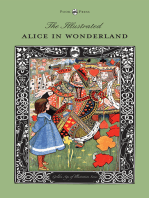

![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)