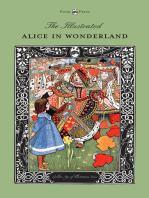Professional Documents
Culture Documents
Pendidikan Inklusif
Uploaded by
Abu Zahlan HusainOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Pendidikan Inklusif
Uploaded by
Abu Zahlan HusainCopyright:
Available Formats
PENDIDIKAN INKLUSIF; ANTARA KONSEP, KEBIJAKAN DAN PRAKTEK
Pembaca yang terhormat, Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan untuk berbicara di Lembaga Administrasi Negara pada sebuah focus group discussion dalam rangka merumuskan menejemen pelayanan berbasis inklusif yang akan dirumuskan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Berikut adalah share saya tentang paper yang saya sajikan dalam forum diskusi yang sangat menarik tersebut. Pendahuluan Seiring dengan perkembangan sejarah perubahan sosial dari masa ke masa, pemahaman orang terhadap keberadaan kelompok berkebutuhan khusus, penyandang cacat, difabel, penyandang ketunaan maupun istilah lain yang dimaksudkan untuk merujuk subyek yang sama (dengan idiologi dan konsepsi yang berbeda) pun telah mengalami banyak perubahan. Secara garis besar, setidaknya ada dua konsepsi yang dalam sepanjang perkembangan sejarah perubahan social serta penteorian difabililitas cukup dominant. Yang pertama adalah pandangan medis/individual, yang melihat dan menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu. Secara ringkas, pandangan ini menganggap kecacatan/impairment sebagai sebuah tragedy personal, dimana impairment selalu diposisikan sebagai akar permasalahan serta penyebab atas hambatan aktifitas serta berbagai bentuk ketidak beruntungan social yang dialami (Barnes and Mercer, 1996). Model/pandangan ini pun diadobsi dalam sebuah instrument internasional yang dipublikasikan oleh WHO pada tahun 1980, yang dikenal dengan ICIDH (International Clasification of Impairment, Disability and Health). Dalam klasifikasi internasional ini, WHO, dengan keterlibatan dominant kelompok-kelompok professional medis, sekali lagi menegaskan hubungan kausal antara impairment /keterbatasan fungsi, disability / ketidak mampuan/hambatan aktifitas, serta handicap / ketidak beruntungan social (WHO 1980, Oliver 1990, Oliver, pada Barnes and Mercer 1996). Adapun pandangan ke dua adalah pandangan/konseptualisasi difabilitas
yang terlahir atas dominasi konsepsi difabel dan bagaimana semestinya lingkungan social memandang diri mereka. Pandangan yang disebut dengan social model, yang belakangan kemudian berkembang menjadi pandangan yang melihat difabilitas dalam pendekatan HAM ini dibangun atas sebuah prinsip dasar bahwa kecacatan/impairment maupun keterbatasan fungsional sesungguhnya tidak pernah mempunyai korelasi langsung terhadap apa yang dikatakan sebagai disability / ketidak mampuan aktifitas, maupun juga partisipasi social (UPIAS 1996, dan Barnes dan Mercer 1996). Disability, , menurut pandangan ini tidak lain dikarenakan atas kegagalan masyarakat, lingkungan serta negara dalam mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan difabel (UPIAS, 1996). Dengan kata lain, disability yang dimaksud merupakan buah dari sebuah interaksi lingkungan yang gagal mengakomodasi keberadaan difabel. Dalam perkembangannya, HAM kemudian mulai mengenali disability issue sebagai sebuah bagian integral atas isu HAM, dimana berangkat dari salah satu prinsip bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang secara inherent melekat pada setiap manusia, maka kondisi social exclusion yang dialami oleh kelompok difabel yang diakibatkan atas interaksi yang gagal tersebut sudah seharusnya dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran hak. Dengan kata lain, jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga semestinya melekat pada setiap individu difabel yang juga mesti dilindungi. Tidak berhenti sampai disitu, langkah-langkah pemenuhan hak dasar, sebagaimana diatur dalam berbagai instrument HAM, yang untuk kelompok difabel akan lebih relevan jika merujuk pada Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) juga semestinya dilakukan dengan memperhatikan prinsip inter dependence, indivisibility and inter related of rights, ya itu bahwa setiap hak bersifat terkait, tergantung dan saling tak terpisahkan satu sama lain. Akhirnya, inclusion pun dipandang sebagai sebuah cara yang paling tepat dalam engejawantahkan pandangan ini. Dalam hal ini, inklusi mestinya dipahami sebagai sebuah kondisi yang menjamin partisipasi penuh setiap manusia dengan berragam keberbedaan, melalui serangkaian akomodasiakomodasi yang harus dilakukan sesuai kebutuhan. Pengertian yang masih abstrak ini, tentunya masih perlu diterjemahkan dengan lebih nyata tentang bagaimana akomodasi-akomodasi kebutuhan tersebut harus dilakukan, jaminan atas partisipasi penuh tersebut akan seperti apa, dan seterusnya. Oleh masyarakat dunia, langkah-langkah mewujudkan
inclusion ke dalam bentuk nyata pun terlihat dengan munculnya berbagai dokumen internasional, perkembangan teori, filosofi akademik, serta perubahan pendekatan dalam menangani kelompok difabel tersebut. Pendidikan inklusif Pendidikan inklusif, yang kini telah mulai dikenal setelah lama diwacanakan di Indonesia sendiri telah mulai berkembang di tingkat internasional sejak cukup lama. Setidaknya, apa bila merujuk pada beberapa dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Hak Anak (1989), Deklarasi Dunia Tentang Pendidikan Untuk Semua (1990), Peraturan Standar Tentang Persamaan Hak Bagi Difabel (1993), dalam beberapa substansinya mempunyai pointer-pointer yang relevan dengan semangat pendidikan inklusif sebagai sebuah penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodasi keberbedaan, keunikan serta keberragaman masing-masing peserta didik. Terlebih apa bila mengacu pada pernyataan salamanca (1994) yang secara lebih mengerucut memberikan guideline yang jelas mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam setting inklusi. Jika sudah boleh dikatakan berjalan, pendidikan inklusif sendiri sudah dimulai beberapa tahun terakhir di Indonesia. Di tingkat dasar, bahkan sudah menjadi keharusan bagi setiap kecamatan untuk memulai sedikitnya satu sekolah yang inklusi. Namun, apa yang sudah dilaksanakan ini pun masih menyisakan beberapa pertanyaan. Setidaknya, layanan inklusi dalam pendidikan yang sudah berjalan ini masih sebatas pada tingkat pendidikan dasar. Sementara, faktanya bahwa angka difabel yang menempuh pendidikan tinggi sudah cukup meningkat dari tahun ke tahun, sehingga mau tidak mau, sudah menjadi tuntutan lembaga pendidikan tinggi untuk mulai memberlakukan dan mengembangkan sistem inklusi. Untuk itu, kreatifitas dan komitmen lembaga pendidikan tinggi merupakan hal yang esensial dalam mengakomodasi kebutuhan tersebut, yang mesti pula dibarengi dengan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi pengembangannya. Di sisi lain, apa yang dimaksud sebagai pendidikan inklusif dalam kontek sistem pendidikan nasional kita agaknya juga masih perlu dikaji dan dikembangkan lebih jauh. Fakta menunjukkan bahwa sepanjang implementasinya, pelaksanaan pendidikan inklusif sejauh ini masih belum mampu menjawab kebutuhan akan keteraksesan serta kualitas pendidikan itu sendiri. Di satu pihak kesiapan hard resources masih menjadi masalah
besar pada sekolah-sekolah inklusi baru-baru ini, yang terkait dengan ketersediaan media belajar, infra struktur, serta berbagai fasilitas sekolah yang aksesibel. Sementara di pihak lain, pengayaan soft resources yang berupa penguasaan pemahaman pengajar serta management lembaga pendidikan akan konsekwensi dari inklusi, kemampuan mengelola pembelajaran dalam setting inklusi, melakukan sistem penilaian, serta modivikasi kurikulum yang menjadi konsekwensi logis dari pendidikan inklusif juga masih menjadi kesulitan di sebagian besar sekolah. Untuk itu, tulisan ini akan mencoba untuk (1) melihat relevansi antara konsep dan kebijakan pendidikan inklusif dalam rangka memberikan kontribusi atas perbaikan-perbaikan yang mungkin untuk dilakukan; dan (2) mendiseminasikan model layanan inklusi pada pendidikan tinggi sebagaimana yang sudah dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga bersama Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) Kerangka Berfikir Mendudukkan pendidikan inklusif sebagai sebuah prinsip dalam penyediaan layanan pendidikan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Inklusi yang ingin coba diterapkan di Indonesia ini harus dipahami secara mendalam bukan hanya dalam tataran abstrak dan teoritis, namun juga harus dapat diterjemahkan secara praktis dan implementatif. Begitu pula, sebelum inklusi dapat sepenuhnya diterapkan, perubahan paradigma di kalangan stake holders yang berpengaruh dalam penyelenggaraan pendidikan harus terjadi secara matang dan tepat. Memaknai Pendidikan inklusif Bagaimana pendidikan inklusif dimaknai merupakan pondasi penting yang harus dibangun untuk dapat mengkonseptualisasikannya dalam tataran praktis. Memahami pendidikan inklusif tidak bisa berhenti sebatas menerima anak didik berkebutuhan khusus pada lembaga pendidikan secara bersama-sama dengan anak-anak lainnya. Lebih dari itu, pendidikan inklusif dibangun atas sebuah ide mulia untuk mengakomodasi keberragaman. Dalam sudut pandang ini, istilah normal tidak lagi dipahami sebagai standar-standar kewajaran yang digunakan untuk mengkategorikan kemampuan anak, melainkan untuk memaknai keberragaman sebagai sesuatu yang normal dalam masyarakat. Demikan pula, adalah normal apa bila ada anak yang pandai dan tidak, kaya dan miskin, dengan
perbedaan ras, suku bangsa, agama, termasuk yang berkebutuhan khusus dan yang tidak dan keberadaan mereka harus diakomodasi dalam sistem pendidikan inklusif(Skjorten, 2001). Dengan demikian, inklusi harus diterjemahkan sebagai bukan saja sebuah affirmative action untuk mengakomodasi pendidikan bagi anak-anak dengan difabilitas saja, tapi lebih dari itu, inklusi memang sebuah upaya untuk mengakomodasi berbagai bentuk keragaman. Dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang pendidikan inklusif, sebenarnya kita berbicara tentang membangun lingkungan / penyelenggaraan pendidikan bagi semua anak (education for all). Dalam kaitannya dengan pendidikan inklusif bagi siswa / peserta didik dengan kebutuhan khusus, lebih jauh Skjorten (2001) mengidentifikasi bahwa ada setidaknya tiga faktor yang harus diakomodasi secara holistik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama adalah lingkungan, yang termasuk di dalamnya adalah respon lingkungan terhadap keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus, tingkat pemahaman dan penguasaan guru terhadap pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan, isi, materi serta metode pembelajaran, serta lingkungan yang lebih luas yang berhubungan dengan lingkungan sosial, ekonomi serta politik, yang secara langsung maupun tidak, keseluruhan akan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan belajar anak. Yang ke dua adalah faktor dalam diri peserta didik yang dapat meliputi rasa ingin tahu, motivasi, inisiatif untuk berinteraksi dan komunikasi, kompetensi sosial, temperamen, kreatifitas, dorongan untuk belajar dan gaya belajar, serta kemampuan. Adapun faktor yang ke tiga adalah hakekat dan tingkat kebutuhan khusus. Ke tiga faktor inilah yang dalam penyelenggaraan seting pembelajaran inklusi mesti diakomodasi ke dalam berbagai bentuk penyesuaian-penyesuaian sebagaimana yang diperlukan. Dengan membaca keterkaitan antara ke tiga faktor di atas, inklusi mempunyai sebuah karakteristik khusus yang sama sekali berubah dari sistem sebelumnya. Jika pada sistem pendidikan segregasi, pendidikan berorientasi kepada keterbatasan anak dengan merujuk pada diagnosa yang dilakukan oleh profesional, inklusi berupaya untuk meninggalkan pemahaman ini. Sesuatu yang dikatakan sebagai kecacatan kemudian tidak lagi dipandang sebagai segalanya atau sesuatu yang serba menentukan, karena potensi dan sesuatu yang potensial untuk dikembangkan dari peserta didik merupakan hal yang paling utama. Demikian pula, adabtasi
lingkungan serta interaksi, proses pembelajaran, media serta metode belajar yang tepat dan sesuai kebutuhan anak menjadi kunci yang harus dipertimbangkan. Tak berhenti sampai disitu, peran orang tua, teman belajar, serta masyarakat di luar sekolah mempunyai kontribusi yang sangat bernilai bagi keberhasilan pencapaian peserta didik dalam seting inklusi. Dalam kontek inilah kemudian pendidikan inklusif menempatkan assessment sebagai tahapan penting (Skjorten, 2001). Tidak mudah dan butuh waktu lama untuk sampai pada tingkat pemahaman ini, namun yang lebih sulit dan menjadi tantangan bagi upaya implementasi pendidikan inklusif yang sejatinya adalah bagaimana menyebarkan pemahaman ini di kalangan guru, profesional yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan , serta stake holder lain yang berhubungan. Yang lebih penting lagi adalah bahwa negara memegang sebuah peran penting dalam mensistematikakan konsep ini melalui berbagai bentuk kebijakan pendidikan yang komprehensif, sehingga konsep ini dapat secara implementatif diterapkan. Kebijakan Belajar dari negara yang telah sepenuhnya mengadopsi inklusi dalam sistem pendidikan nasionalnya seperti Norwegia mungkin dapat menjadi awal yang baik untuk melihat relefansi dan kompatibilitas kebijakan yang sudah kita miliki dalam menterjemahkan dan me-regulate pelaksanaan pendidikan inklusif. Adanya sebuah kebijakan yang mampu menjadi acuan pelaksanaan pendidikan inklusif merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk mendukung implementasinya. Dan baik atau tidaknya sebuah kebijakan, dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mempunyai relevansi dengan prinsip utama dari sesuatu yang akan diatur dalam kebijakan tersebut. Johnsen menyatakan bahwa setidaknya ada tiga prinsip utama dari penyelenggaraan pendidikan inklusif yang keseluruhan bermuara pada pemahaman inti bahwa adalah hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dalam seting lokal bersama dengan masyarakat lainnya. Ke tiga prinsip utama tersebut adalah (1) bahwa setiap anak semestinya dapat menjadi bagian yang integral dari komunitas lokalnya dan kelas atau
kelompok reguler; (2) bahwa kegiatan pembelajaran diatur melalui tugastugas belajar yang kooperatif, berorientasi pada pembelajaran individual, serta mempunyai sifat fleksibel dalam pemilihan materi; dan (3) bahwa guru bekerjasama dan memiliki pengetahuan tentang strategi pembelajaran dan kebutuhan pengajaran umum, khusus dan individual, dan memiliki pengetahuan tentang cara menghargai pluralitas perbedaan individual dalam mengatur aktivitas kelas (Johnsen, 2001). Bagaimana konsep tentang pendidikan inklusif di Indonesia untuk selanjutnya dapat dituangkan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional tentu masih perlu dikaji, walaupun sebetulnya sudah cukup terlihat pada peraturan menteri pendidikan nasional no.70 tahun 2009 yang baru-baru ini dikeluarkan. Dan semari memperjelas struktur konsep pendidikan inklusif dalam tatanan sistem pendidikan nasional kita, ke tiga prinsip yang ditawarkan oleh Johnsen tersebut mungkin bisa dijadikan tolok ukur dalam menganalisa keberadaan kebijakan pendidikan kita dalam mengakomodasi dan meregulasi keberadaan pendidikan inklusif. Pembahasan a. Idiologi Pendidikan inklusif dan Kebijakan Jika pada bagian terdahulu saya mencoba mengelaborasi pemaknaan ideal atas pendidikan inklusif, pada bagian ini, tulisan ini akan mencoba mengulas pemaknaan pendidikan inklusif di Indonesia dengan melihat rangkaian kebijakan yang ada. Jaminan atas kesetaraan hak untuk memperoleh pendidikan, secara tegas telah tercantum pada undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1 dan 2, yang bunyinya sebagai berikut: 1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran. 2. Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Lebih jauh pada undang-undang no.20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional, penjelasan tentang penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara berkebutuhan khusus dijelaskan pada pasal 5 ayat 1-2. Pada ayat 2 dari undang-undang tersebut berbunyi Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Istilah pendidikan khusus sebagaimana tercantum pada kutipan ayat diatas jelas bukan berasal dari terminologi pendidikan inklusif. Karena,
secara jelas, inklusi mengakomodasi kekhususan peserta didik dan kebutuhan khususnya, dan bukan berarti penyelenggaraan pendidikan secara khusus yang justru lebih tepat disamakan dengan pendidikan segrasi / luar biasa. Sampai disini sebetulnya, sudah cukup jelas bahwa ternyata, inklusi belum merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional kita. Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ada sekarang ini, dengan melihat UU no.20 tersebut masih bisa dikatakan sebagai sesuatu yang setengah hati. Mencoba menelusuri lebih jauh, dalam penentuan standard pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah no.19 tahun 2005, tidak pula disebutkan standarisasi pelaksanaan pendidikan inklusif. Hanya ada satu kalimat ya itu Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusiff harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus Secara bebas, kalimat tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa seolah-olah, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus menanggung sendiri hal-hal yang berkait dengan penyiapan tenaga pengajar yang mampu menyelenggarakan pembelajaran inklusi. Disana sama sekali tidak muncul adanya peran pemerintah dalam mengakomodasi penyiapan pengajar yang mempunyai kompetensi tersebut. Sementara, apa bila merujuk pada tiga faktor penyelenggaraan pendidikan inklusiff secara holistik (lingkungan, kondisi anak dan kebutuhan khusus/difabilitas), setidaknya muncul dua kebutuhan besar yang harus diakomodasi serta distandardkan sebagai bagian dari implementasi inklusi. Ke dua hal tersebut yaitu standard aksesibilitas fisik yang berisi adabtasi lingkungan fisik yang harus ditetapkan dalam rangka mendukung terciptanya lingkungan yang free-barrior untuk mendukung pendidikan inklusif, serta aksesibilitas non-fisik yang dapat berupa aturan-aturan atau prosedur yang menjamin partisipasi penuh peserta didik dengan kebutuhan khusus dalam pendidikan / kegiatan persekolahan, adabtasi kurikulum, metode pembelajaran, serta layanan administrasi. Hal tersebut semestinya juga terbaca sebagai komponen penyelenggaraan pendidikan inklusif yang harus dirangkum secara holistik dalam sebuah standard penyelenggaraan pedidikan inklusi. Pembacaan yang hanya melihat pentingnya standar pengajar yang punya kompetensi dalam pengelolaan pembelajaran inklusif sebagaimana yang sudah ada pada PP no.19 ini sekali gus dapat dipahami
bahwa inklusi yang tertuang pada sistem pendidikan nasional kita sekali lagi masih inklusi yang setengah hati dan belum mau mendudukkan keberadaan lingkungan yang lebih luas sebagai faktor yang juga menentukan keberhasilan pembelajaran. Beberapa kekhawatiran di atas sebetulnya telah cukup terjawab dengan dikeluarkannya peraturan menteri pendidikan nasional no.70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusiff. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, beberapa hal teknis seperti keterlibatan pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusiff sudah cukup terlihat. Hanya saja, satu hal yang masih menjadi catatan adalah penyelenggaraan sekolah inklusif yang masih berbasis penunjukan kiranya tidaklah sesuai dengan prinsip pendidikan inklusiff yang salah satunya adalah bahwa setiap anak semestinya dapat menjadi bagian yang integral dari komunitas lokalnya dan kelas atau kelompok reguler. Akan lebih fair sebetulnya jika penyelenggaraan satuan pendidikan inklusiff ditentukan berdasarkan data persebaran difabel / anak berkebutuhan khusus. Namun sayangnya, masalah ketersediaan data pun masih menjadi masalah tersendiri yang agaknya sulit terpecahkan. Tetapi, dengan model penunjukan sebagaimana diatur dalam PERMEN tersebut, prinsip untuk tetap memberikan akses pendidikan yang integral bagi setiap anak dalam komunitas lokalnya akan sulit terpenuhi karena tidak setiap sekolah akan menerima siswa dengan kebutuhan khusus. Sama pentingnya dengan evaluasi belajar, dalam praktek pendidikan inklusif sesungguhnya dikenal pula assessment sebagai sebuah proses pengukuran kemampuan serta kebutuhan akan berbagai adaptasi, program pembelajaran maupun layanan-layanan khusus yang diperlukan. Sayangnya, proses ini pun belum terbaca dalam peraturan kependidikan kita terkait dengan pendidikan inklusif ini. Jika evaluasi belajar berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa, maka pada saat yang sama, assessment berfungsi untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan dan kebutuhan, yang selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun program pembelajaran. Dalam setting inklusi, keberhasilan pembelajaran ditentukan salah satunya oleh ketepatan program pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil need assessment masingmasing peserta didik. Oleh karenanya, sangat penting kiranya untuk menjadikan assessment sebagai bagian dari prosedur dalam penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, serta membakukannya dalam sebuah kebijakan.
Berangkat dari pandangan sekilas mengenai kebijakan pendidikan inklusiff tersebut, akan lebih pas kiranya bila dilanjutkan pada analisa fakta mengenai praktek dan impementasi pendidikan inklusif. Untuk itu, pada bagian berikutnya dari tulisan ini akan mencoba dipaparkan bagaimana praktek pendidikan inklusif di-design dan dilaksanakan di Universitas Islam Negeri melalui Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD).
b. Membangun Role Model Praktek Inklusi di Perguruan Tinggi; Studi Kasus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Penerimaan UIN Sunan Kalijaga terhadap mahasiswa difabel sebenarnya sudah dimulai sejak lama, bahkan sudah sejak belasan tahun yang lalu. Pada saat itu, belum ada pemahaman ataupun pemikiran tentang inklusi. Mahasiswa difabel hanya diterima pada program studi yang dipandang memungkinkan tanpa fasilitasi ataupun adaptasi tertentu. Mungkin, bila diidentikkan, apa yang dilakukan oleh UIN pada saat itu adalah lebih buruk dari pendidikan terpadu di tingkat sekolah dasar dan menengah sekalipun, karena belum terfikir segala hal yang menjadi kebutuhan mahasiswa difabel dalam menjalani proses pembelajaran. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyaknya difabel yang belajar di UIN Sunan Kalijaga memunculkan kesadaran beberapa dosen dan pimpinan universitas akan pentingnya mengakomodasi difabel dalam sebuah seting pendidikan yang diidealkan sebagai inklusi. Prinsip dasar yang melandasi komitmen ini adalah bahwa difabel adalah juga warga negara dan hamba Tuhan yang sama kedudukannya dengan manusia lainnya, dan dengan demikian, adalah hak mereka juga untuk memperoleh layanan pendidikan yang inklusif dan mengakomodasi kebutuhankebutuhan mereka. Dan UIN sebagai perguruan tinggi berbasis islam harus mampu dan berani untuk mulai memberikan contoh yang diharapkan dapat diikuti oleh lembaga pendidikan tinggi lain di Indonesia. Berbekal pemahaman dan sumber daya yang terbatas tersebut, pada
tahun 2006, didirikanlah Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD). Dua fungsi utama yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh Pusat Studi dan Layanan Difabel ini adalah: 1. Fungsi praktis menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mahasiswa difabel. Dalam menjalankan fungsi ini, beberapa hal yang sudah dikembangkan diantaranya adalah: - Penyediaan teknologi adaptif difabel yang meliputi komputer bicara, digital talking book, akses internet bagi mahasiswa difabel, serta unit transkripsi yang bekerja mentranskripsi referensi ke dalam soft files. - Mengorganisir relawan yang berasal dari mahasiswa UIN maupun dari luar kampus UIN. Memberikan fasilitas pendampingan (belajar dan ujian). - Menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan penunjang akademik dan belajar seperti komputer dan penulisan ilmiah dalam rangka mendukung keberhasilan mahasiswa dalam belajar. - Melakukan need assessment terhadap mahasiswa difabel, dan bersama dengan pengajar, merumuskan bentuk-bentuk adaptasi yang diperlukan dalam proses pembelajaran. - Bersama pengajar, berbagai unit layanan seperti TU, perpustakaan, penyelenggara KKN dan praktikum serta unit lain, PSLD juga telah berhasil merumuskan standard operasi dan prosedur(SOP) PEMBELAJARAN DAN LAYANAN AKADEMIK INKLUSIF YANG MASIH AKAN TERUS DIKAJI DAN DISEPURNAKAN. - Bersama dengan Perpustakaan UIN, saat ini PSLD juga sedang menggagas tersedianya fasilitas perpustakaan yang aksesibel, mulai dari ketersediaan referensi sampai dengan teknologi adaptif pendukung belajar dalam bentuk blind corner.
2. Fungsi strategis (advocacy initiative) - Melakukan kajian secara berkesinambungan dan mendalam terkait dengan isu-isu difabilitas, yang lebih difokuskan pada akses difabel pada pendidikan tinggi. Sampai dengan saat ini, kegiatan kajian yang kami laksanakan masih dalam bentuk kajian internal yang ditujukan untuk menggali permasalahan serta kebutuhan difabel serta alternatif solusi yang mungkin dilakukan oleh PSLD dalam menjawab permasalahan / kebutuhan tersebut. - Memediasi proses-proses konsultasi antara difabel dan pimpinan universitas, dosen, maupun pihak penyedia layanan di tingkat UIN dalam rangka mewujudkan kampus UIN yang inklusif dan ramah difabel. - Melakukan berragam aktifitas kampanye baik di kampus maupun di luar kampus yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat (kampus dan non kampus) akan pentingnya menghormati dan mengakomodasi hak difabel akan pendidikan inklusiff. - Membangun jaringan pendidikan inklusif di perguruan tinggi. Kendala dan Pembelajaran Praktek yang telah dikembangkan oleh PSLD dalam kurun waktu 3-4 tahunan ini tidaklah berjalan dengan mulus dan mudah seperti yang diharapkan. Salah satu kendala utamanya adalah minimnya pemahaman di tingkat UIN, bahkan kawan-kawan yang terlibat dalam tim PSLD sendiri mengenai hal-hal yang terkait dengan difabilitas, bahkan pendidikan inklusif. Sebagaimana diketahui, di UIN Sunan Kalijaga tidak ada disiplin ilmu / jurusan yang terkait langsung dengan pendidikan bagi difabel, sehingga memulai proses ini, bagi kami bagaikan meraba-raba dalam gelap. Namun, justru dari situasi inilah sebenarnya, ada sebuah proses pembelajaran besar bahwa ternyata segala sesuatunya dapat dirumuskan bersama dengan melihat siuasi lokal. Dengan pemahaman sederhana bahwa inklusi adalah tentang pelibatan / partisipasi penuh dengan mengakomodasi kebutuhan dan keberbedaan, ada sebuah keyakinan bahwa merekalah yang memahami kebutuhan mendasr mereka sehingga segala sesuatunya mesti dirumuskn dengan memberikan porsi keterlibatan penuh mahasiswa difabel. Kendala lain adalah keterbatasan sumber daya pendukung dalam pengembangan layanan inklusi itu sendiri. Sejauh ini, praktek yang berlangsung di UIN Sunan Kalijaga memang memperoleh dukungan penuh
baik secara moral maupun finansial dari pimpinan unifersitas. Namun, disadari bahwa untuk mencapai bentuk inklusi yang ideal, masih banyak adaptasi dan pengembangan yang harus dilakukan baik berupa hard resources yang berbentuk sarana / prasarana maupun soft resources seperti pengembangan kapasitas dan penyadaran dosen dan staf, peningkatan kreatifitas dosen, pengembangan / modifikasi kurikulum, serta penelitian dan pengembangan. Dan jika melihat kebutuhan pengembangan yang sebegitu besar itu, rasanya dukungan dari unifersitas saja tidak lah cukup. Belum lagi apa bila berfikir tentang bagaimana model semacam ini bisa direplikasikan di perguruan tinggi lain yang tentu membutuhkan banyak sumberdaya yang termasuk didalamnya berupa pendanaan. Untuk itu, peran pemerintah melalui alokasi anggaran pengembangan layanan inklusi di perguruan tinggi rasanya menjadi cukup beralasan untuk direalisasikan. Kesimpulan Sebagai kesimpulan, tulisan ini telah mencoba mempersandingkan antara konsep pendidikan inklusif yang sejatinya dengan kerangka kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Dari sebuah analisa perbandingan yang sederhana tersebut, tulisan ini meyakini bahwa sistim pendidikan nasional, melalui berbagai perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang ada belumlah secara penuh mengadopsi pendidikan inklusif sebagai salah satu pendekatan dan prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Mungkin bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah fase peralihan antara segregasi ke inklusi, dan jika memang benar itu yang terjadi, maka harus ada penyempurnaan kebijakan dengan mengadopsi paradigma pendidikan inklusif yang sesungguhnya. Pada bagian lain dari tulisan ini juga telah diulas sebuah studi kasus pengembangan layanan pendidikan inklusiff di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berdasar pada studi kasus tersebut, satu hikmah yang dapat diyakini adalah bahwa pendidikan inklusif hanya dapat terlaksana dengan komitmen penuh para penyelenggara pendidikan. Faktanya adalah bahwa perubahan menuju inklusi harus dimulai dengan sebuah evolusi pola berfikir serta cara pandang terhadap keberbedaan dan keragaman yang harus diakomodasi, dan bukan keseragaman yang harus diperbandingkan. Sebelum perubahan paradigma ini terjadi, maka seperti apapun inklusi yang dilakukan hanya akan menjadi sebuah bentuk lain dari segregasi yang lebih tersamarkan.
You might also like
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19653)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5783)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2475)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionFrom EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (12941)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19993)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionFrom EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2391)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (2552)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6503)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)From EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (7769)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationFrom EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationRating: 4 out of 5 stars4/5 (2385)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (3265)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksFrom EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksRating: 4 out of 5 stars4/5 (7086)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersFrom EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersRating: 4 out of 5 stars4/5 (2306)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleFrom EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HoleRating: 4 out of 5 stars4/5 (4609)
- Don Quixote: [Complete & Illustrated]From EverandDon Quixote: [Complete & Illustrated]Rating: 4 out of 5 stars4/5 (3845)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)From EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (4345)























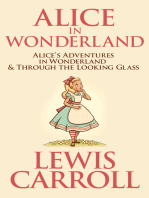

![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)